Bab 3 – Rumah di Arena
• The House on the Borderland •
MAKA, setelah beberapa lama, sampailah aku ke pegunungan. Arah perjalananku pun berubah; aku mulai bergerak menyusuri kaki-kaki gunung, hingga tiba-tiba kusadari bahwa aku telah berada tepat di depan sebuah celah raksasa yang menganga di tubuh pegunungan itu. Melalui celah itulah aku dibawa masuk, bergerak tanpa tergesa.
Di kedua sisiku, menjulang dinding-dinding curam, seolah batu cadas tegak lurus tanpa celah. Jauh di atas sana, samar kulihat seutas pita merah tipis, tempat mulut jurang terbuka di antara puncak-puncak yang mustahil dijangkau.
Di dalam, hanya ada suram, pekat dan muram, bersama keheningan dingin yang mencekam. Untuk beberapa lama aku terus maju, hingga akhirnya tampak di kejauhan cahaya merah pekat—tanda bahwa aku hampir mencapai ujung jurang.
Beberapa saat kemudian, aku pun keluar, menatap ke luar jurang pada sebuah amfiteater pegunungan yang luar biasa luas. Namun gunung-gunung itu, betapa pun megah dan dahsyatnya, tak segera menarik perhatianku; sebab aku terperangah tak percaya melihat, pada jarak bermil-mil jauhnya, tepat di tengah arena itu, berdiri sebuah bangunan raksasa, tampak seolah-olah terbuat dari giok hijau.
Namun bukan bangunan itu sendiri yang membuatku terkejut, melainkan kenyataan—yang makin lama makin jelas bagiku—bahwa tak ada satu pun perbedaan mendasar antara bangunan kesepian itu dengan rumahku sendiri, kecuali warna dan ukurannya yang luar biasa besar.
Sekian lama aku hanya bisa menatap terpaku. Bahkan saat itu pun sulit bagiku mempercayai apa yang kulihat. Sebuah pertanyaan pun terbentuk di benakku, terus berulang tanpa henti:
Apa artinya ini? Apa artinya ini?
Dan aku sama sekali tak mampu menjawab, bahkan dengan imajinasi paling liar sekalipun. Aku hanya sanggup merasa takjub bercampur gentar.
Aku terus menatapnya, menemukan semakin banyak kemiripan yang membingungkanku. Hingga akhirnya, letih dan penuh tanda tanya, aku berpaling dari rumah itu, untuk menilik sisa tempat asing yang kini kumasuki.
Sejauh ini, perhatianku memang hanya tertuju pada Rumah; sekadar lirikan singkat kualihkan ke sekeliling. Sekarang, saat kuluangkan pandanganku, barulah aku menyadari di tempat macam apa aku berada.
Arena itu—demikian kusebut—tampak bundar sempurna, berdiameter sepuluh hingga dua belas kilometer, dengan Rumah berdiri tepat di pusatnya. Permukaan tanah, seperti di Dataran, memiliki tampilan aneh, samar berkabut, meski bukanlah kabut sejati.
Dari pengamatan cepat itu, pandanganku melayang ke lereng pegunungan yang mengitari. Betapa sunyinya mereka. Aku rasa kesunyian terkutuk inilah yang paling menyiksaku, lebih dari apa pun yang kulihat atau kubayangkan.
Aku menatap ke atas, ke tebing-tebing besar yang menjulang tinggi. Di sana, kemerahan yang tak berwujud membuat segala sesuatu tampak buram.
Dan tiba-tiba, saat mataku meneliti dengan penasaran, ketakutan baru menyergapku; sebab jauh di antara puncak kabur di sebelah kanan, kulihat sesosok hitam raksasa, bagai makhluk rimba purba.
Semakin lama semakin jelas. Ia memiliki kepala kuda raksasa, dengan telinga menjulang, dan seakan menatap teguh ke bawah, ke dalam arena. Sikapnya memberi kesan kewaspadaan abadi—seolah telah menjaga tempat muram ini sepanjang kekekalan yang tak terhitung.
Perlahan-lahan sosok itu kian nyata bagiku; lalu, tiba-tiba, mataku tertarik pada sesuatu yang lebih jauh, lebih tinggi, di antara tebing. Lama aku menatapnya dengan rasa gentar. Anehnya, aku diliputi kesadaran samar akan sesuatu yang tak sepenuhnya asing—seolah ada memori tua yang bangkit di benakku.
Sosok itu hitam, dengan empat lengan ganjil. Wajahnya samar, tetapi di lehernya kulihat benda-benda pucat menggantung. Perlahan detailnya tampak, dan aku pun ngeri menyadari bahwa itu adalah tengkorak.
Lebih ke bawah, tubuhnya dililit sabuk lain, yang warnanya sedikit lebih muda dari hitam tubuhnya. Saat aku masih berusaha menebak apa sosok itu, tiba-tiba sebuah kenangan melintas: aku tahu kini bahwa yang kulihat adalah gambaran mengerikan dari Kali, dewi kematian Hindu.
Kenangan lain dari masa mudaku sebagai pelajar ikut menyeruak. Pandanganku kembali jatuh pada makhluk berkepala kuda itu.
Seketika aku mengenalinya sebagai dewa Mesir kuno: Set, atau Seth, Sang Penghancur Jiwa.
Dengan pengetahuan itu, pertanyaan-pertanyaan besar menyerbu pikiranku. Dua dari…! Aku terhenti, berusaha berpikir. Hal-hal di luar jangkauan imajinasi menekan benakku.
Samar-samar, aku mulai melihat… para dewa kuno dari mitologi! Aku mencoba memahami ke mana semua ini mengarah. Pandanganku berpindah, bergetar, di antara keduanya. Jika—
Sebuah pemikiran datang cepat, dan aku berpaling, menatap cepat ke arah tebing muram di sisi kiri. Sesuatu menjulang dari bawah sebuah puncak besar, sosok kelabu.
Aku heran mengapa aku tak melihat itu sebelumnya, lalu ingat bahwa bagian tersebut memang belum kutatap. Kini ia tampak lebih jelas. Sosok kelabu, dengan kepala luar biasa besar; namun tanpa mata. Bagian wajah itu kosong.
Kini kusadari ada makhluk-makhluk lain di antara gunung. Lebih jauh, di sebuah undakan tinggi, kulihat massa pucat, tak beraturan, menjijikkan. Hampir tak berbentuk, kecuali wajah setengah binatang yang busuk, menatap ke luar dari tengah tubuhnya.
Lalu kulihat lainnya—ratusan jumlahnya. Mereka muncul dari bayangan. Beberapa segera kukenal sebagai dewa-dewa mitologi; lainnya benar-benar asing bagiku, begitu asing hingga pikiran manusia tak sanggup membayangkannya.
Ke kiri dan ke kanan, pandanganku menemukan lebih banyak lagi. Pegunungan itu penuh dengan makhluk aneh—dewa-dewa binatang, dan Kengerian yang begitu keji, begitu biadab, hingga kata-kata tak layak lagi untuk menggambarkannya.
Dan aku—aku diliputi rasa ngeri yang menggunung, takut, dan muak yang tak terkatakan; namun, meski begitu, aku justru dilanda rasa ingin tahu.
Adakah, setelah semua ini, sesuatu yang sesungguhnya dalam pemujaan kafir kuno itu? Sesuatu lebih dari sekadar pengkultusan manusia, hewan, atau unsur alam? Pikiran itu mencengkeramku—adakah?
Kemudian, sebuah pertanyaan kembali terngiang. Apa sebenarnya mereka itu—para dewa-berwujud-binatang, dan yang lainnya?
Mula-mula, mereka tampak bagiku tak lebih dari sekadar monster pahatan yang ditebarkan sembarangan di antara puncak-puncak dan tebing-tebing terjal di pegunungan sekeliling. Namun, ketika kuamati dengan lebih sungguh-sungguh, pikiranku mulai menjangkau ke kesimpulan-kesimpulan baru.
Ada sesuatu pada mereka—semacam vitalitas diam yang tak terkatakan—yang membisikkan pada kesadaranku yang kian terbuka sebuah keadaan hidup-dalam-kematian.
Bukan kehidupan seperti yang kita pahami, melainkan suatu wujud keberadaan tak manusiawi, menyerupai tidur panjang tanpa akhir—suatu kondisi di mana mungkin saja mereka akan terus bertahan, selamanya.
“Abadi!” kata itu meloncat begitu saja dalam pikiranku; dan seketika aku bertanya-tanya, mungkinkah inilah keabadian para dewa?
Dan lalu, di tengah perenungan dan keherananku itu, sesuatu terjadi. Hingga saat itu, aku masih berdiri di balik bayangan mulut jurang besar. Kini, tanpa kehendakku, aku terdorong keluar dari setengah kegelapan itu dan mulai bergerak perlahan melintasi arena—menuju Rumah itu.
Seketika, segala pikiran tentang Bentuk-bentuk raksasa di atas sana lenyap; aku hanya bisa menatap, dengan rasa ngeri, pada bangunan kolosal yang mendekat padaku tanpa ampun. Namun, meskipun kuperhatikan dengan saksama, aku tak menemukan sesuatu yang baru dari yang telah kulihat sebelumnya, dan perlahan-lahan, kegelisahanku pun sedikit reda.
Tak lama kemudian, aku telah sampai di titik yang lebih dari separuh jarak antara Rumah dan ngarai. Di sekelilingku terbentang kesunyian mutlak tempat itu, dengan sepi yang tak terpecah.
Dengan mantap, aku kian dekat ke bangunan raksasa itu. Lalu tiba-tiba, mataku menangkap sesuatu—sosok besar yang berkeliling salah satu penopang masif Rumah, lalu tampak sepenuhnya.
Ia begitu besar, bergerak dengan langkah aneh yang menyerupai lompatan, hampir tegak layaknya manusia. Ia telanjang bulat, dan tubuhnya memancarkan cahaya redup aneh.
Namun bukan tubuhnya yang paling menghantui, melainkan wajahnya. Wajah seekor babi.
Diam-diam, penuh perhatian, aku mengamati makhluk mengerikan itu, melupakan ketakutanku sejenak karena terhisap oleh rasa ingin tahu atas gerak-geriknya. Ia berputar mengelilingi bangunan, langkahnya berat, berhenti di tiap jendela untuk mengintip dan mengguncang terali besi yang melindunginya—sama seperti di rumahku.
Setiap kali sampai di sebuah pintu, ia mendorongnya, meraba pengaitnya dengan hati-hati. Jelas, ia sedang mencari jalan masuk.
Kini, aku sudah kurang dari seperempat mil dari bangunan itu, dan tetap saja aku didorong maju. Mendadak, makhluk itu berbalik, menatap buas ke arahku. Mulutnya menganga, dan untuk pertama kalinya, kesunyian tempat terkutuk itu pecah oleh suara dalam, menggelegar, yang membuat bulu kudukku meremang lebih hebat lagi.
Seketika, aku sadar ia sedang melesat ke arahku—cepat, tanpa suara. Dalam sekejap, ia telah memangkas setengah jarak di antara kami. Dan aku—aku tak berdaya, terus terbawa untuk menemuinya.
Seratus meter lagi, dan kebuasan wajah babi raksasa itu melumpuhkanku dengan ngeri yang tak terperikan. Aku nyaris menjerit dalam puncak ketakutanku; dan ketika rasa putus asa mencapai ujungnya, aku tersadar bahwa aku sedang menatap ke bawah, ke arena, dari ketinggian yang kian cepat meninggi.
Aku terangkat, terangkat. Dalam waktu yang tak bisa kupahami, aku telah melayang ratusan meter di udara.
Di bawah sana, tempat aku berdiri tadi kini dihuni oleh makhluk babi itu. Ia berjongkok dengan keempat kakinya, mengendus dan mengais tanah layaknya babi hutan sejati. Sesaat kemudian ia berdiri lagi, menjulurkan tangan ke atas, dengan raut wajah penuh hasrat yang tak pernah kulihat pada makhluk dunia ini.
Aku terus naik. Beberapa menit saja, seakan-akan, dan aku sudah berada jauh di atas pegunungan—mengambang sendirian, jauh, di tengah merahnya langit. Jauh di bawah, arena itu tampak samar, dengan Rumah raksasa yang kini tak lebih dari noktah hijau kecil. Sosok babi itu tak tampak lagi.
Tak lama, aku melayang melintasi pegunungan, keluar ke atas hamparan luas Dataran. Nun jauh di sana, ke arah matahari berbentuk cincin, tampak sebuah kabut kabur.
Aku menatapnya sambil lalu, dengan acuh. Sekilas, ia mengingatkanku pada pandangan pertama ketika aku melihat amfiteater pegunungan itu.
Dengan rasa letih, aku mendongak ke cincin api raksasa itu. Betapa anehnya ia! Dan ketika aku menatap, dari pusat hitamnya memancar semburan nyala api yang begitu terang dan mendadak.
Dibandingkan dengan inti hitamnya, semburan itu tak berarti; namun, dalam dirinya sendiri, ia sungguh menakjubkan. Dengan minat yang bangkit kembali, aku memperhatikannya saksama, mencatat kilau dan gejolak anehnya.
Lalu, tiba-tiba, seluruhnya meredup, kehilangan wujud, dan lenyap dari pandangan.
Dengan terheran, aku melongok ke bawah ke arah Dataran, yang masih terus kutinggalkan di bawah. Seketika itu pula aku dikejutkan oleh hal baru. Dataran—segalanya—telah lenyap, hanya tersisa samudra kabut merah terbentang di bawahku.
Perlahan, saat kupandang, ia makin menjauh, lalu memudar, larut ke dalam misteri merah samar yang membentang di atas malam tanpa dasar. Dan akhirnya, bahkan itu pun tiada; aku terbungkus dalam kegelapan tak berbentuk, tanpa cahaya, tanpa arah.
Dukung Penulis/Penerjemah Novel Favoritmu
Login untuk memberikan vote dukungan
💖 Suka baca cerita ini?
Bantu KlikNovel menerjemahkan lebih banyak novel public domain seperti The House on the Borderland karya William Hope Hodgson ini. Scan QR Code untuk berdonasi via Saweria 🙏
📝 Belum ada komentar untuk bab ini. Jadilah yang pertama berkomentar!



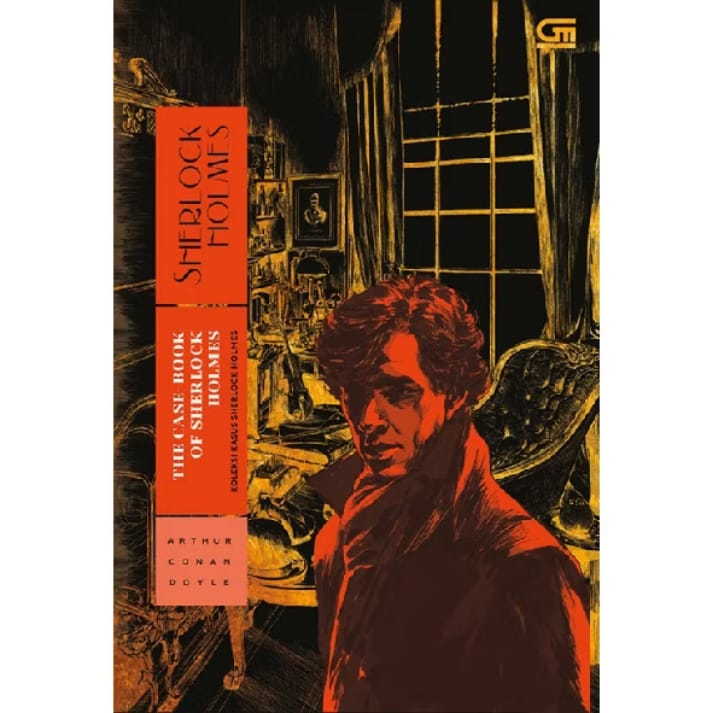


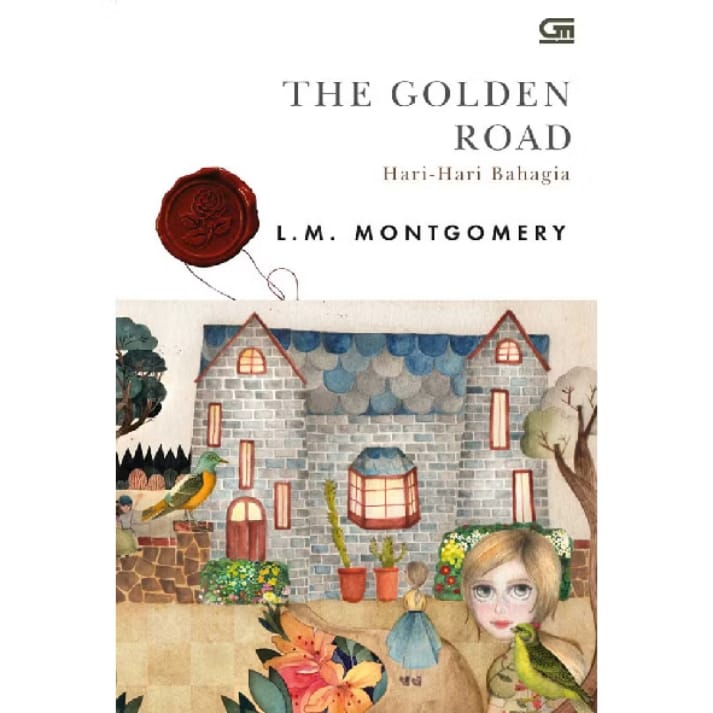



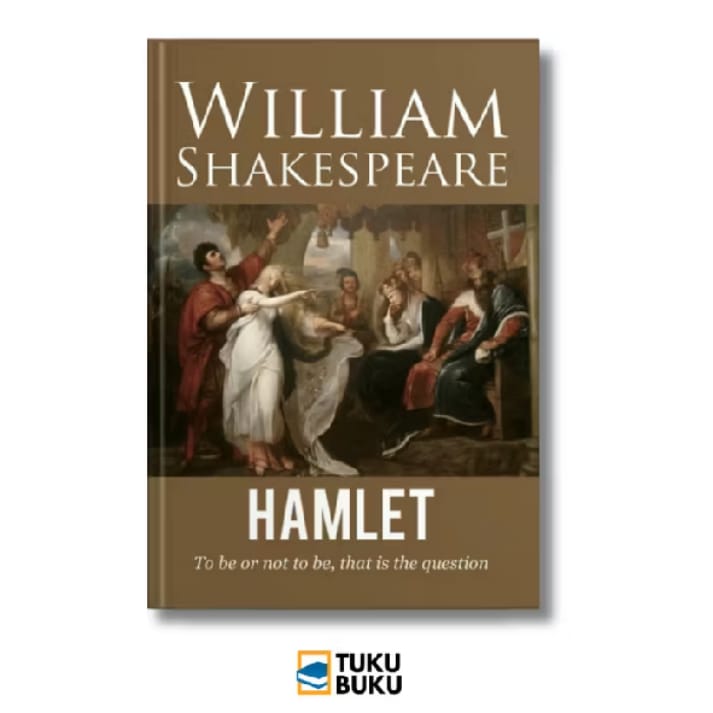


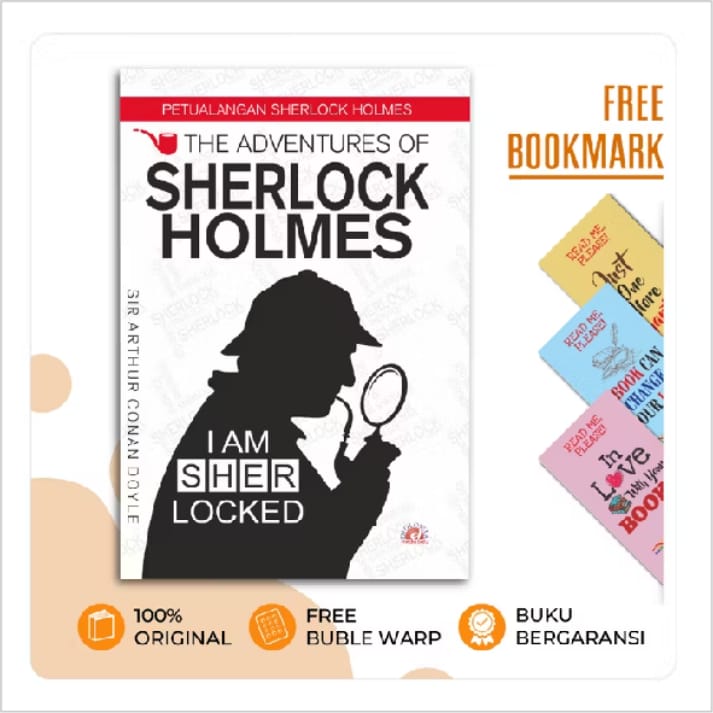
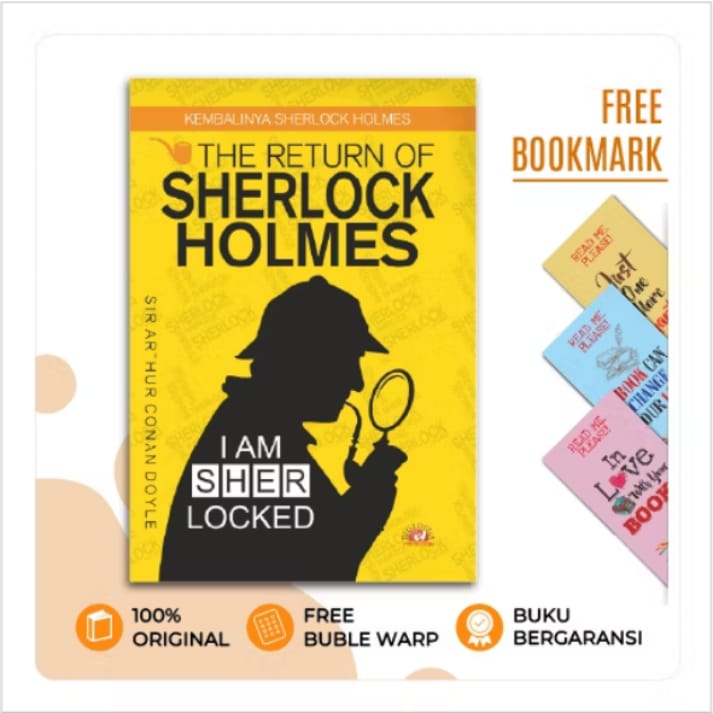
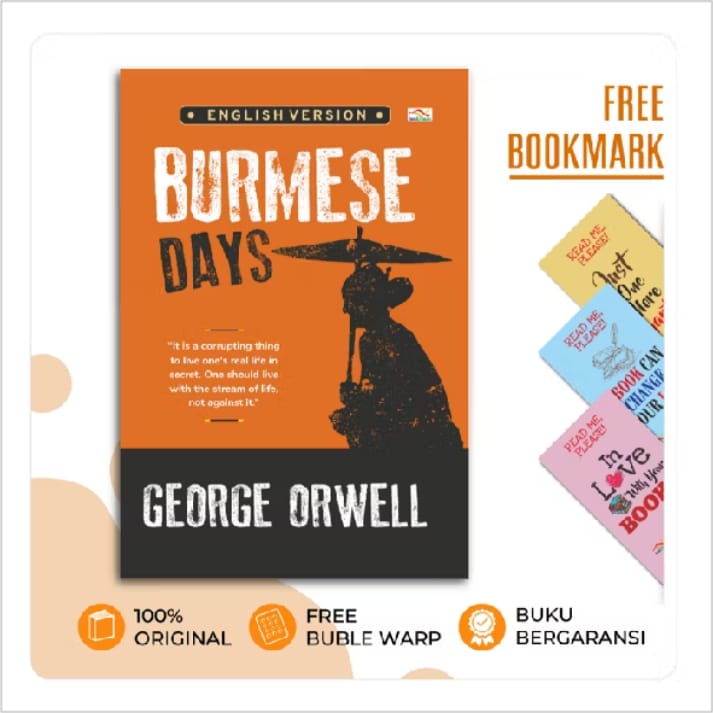

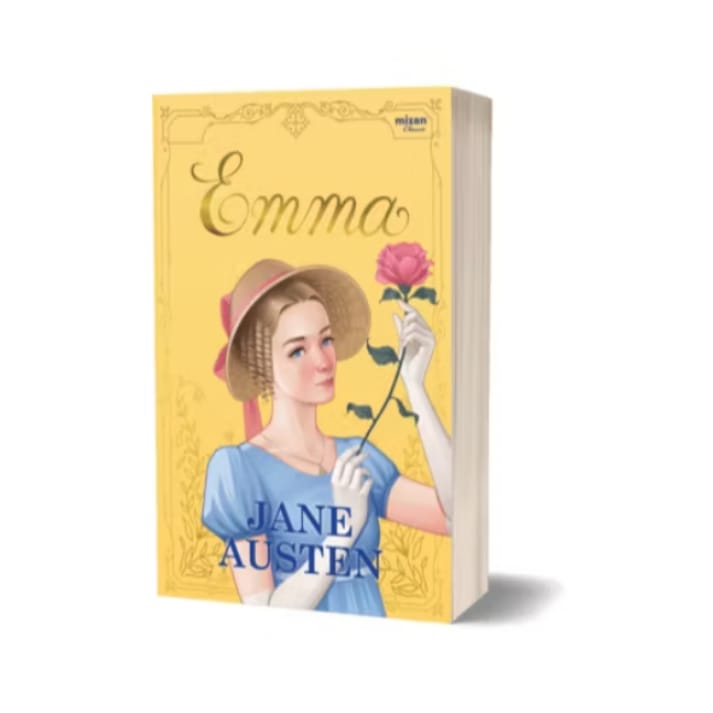
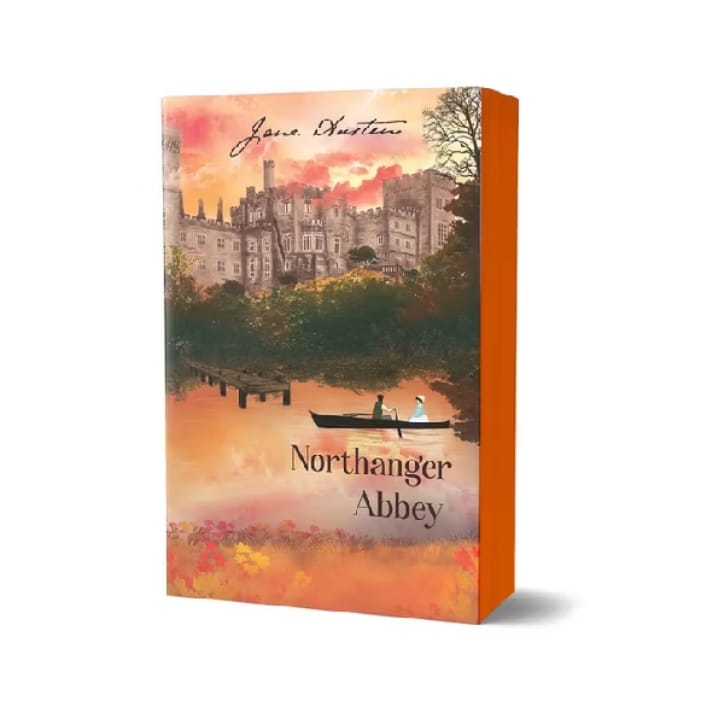

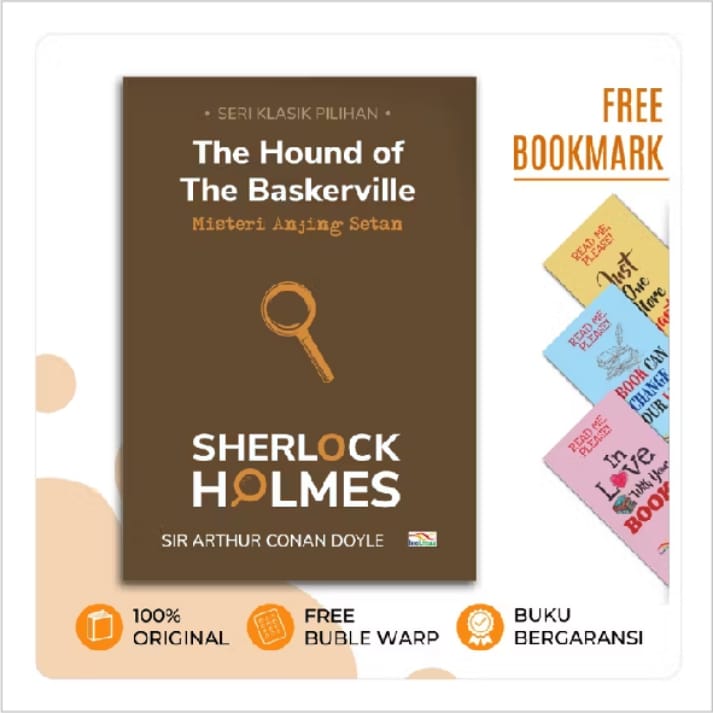


Silakan login untuk meninggalkan komentar.