Bagian 1 — Rumah Warisan Keluarga
SUNGGUH jarang orang biasa seperti aku dan John bisa menginap musim panas di rumah warisan keluarga.
Sebuah rumah bergaya kolonial, milik turun-temurun—kalau boleh berandai-andai, mungkin rumah berhantu!—dan mencapai puncak romantisme. Tapi tentu, itu harapan yang terlalu tinggi.
Meski begitu, aku dengan bangga mengakui bahwa ada sesuatu yang ganjil pada rumah ini.
Kalau tidak, mengapa harganya begitu murah? Dan kenapa rumah sebagus ini dibiarkan kosong begitu lama?
John, tentu saja, menertawaiku. Tapi itu sudah jadi bagian dari pernikahan, bukan?
John sangat praktis, terlalu praktis malah. Ia tak punya kesabaran terhadap keyakinan tanpa bukti, alergi pada takhayul, dan terang-terangan mencemooh hal-hal yang tak bisa dirasa, dilihat, atau diukur dengan angka.
John adalah seorang dokter. Mungkin itu juga—(aku tak akan pernah mengatakan ini pada siapa pun, tapi kertas mati ini adalah tempat yang aman)—mungkin itu salah satu alasan kenapa aku tak lekas sembuh.
Karena ia tidak percaya bahwa aku sakit!
Jadi apa yang bisa kulakukan?
Jika seorang dokter terkemuka, yang kebetulan juga suamimu sendiri, memberi tahu teman dan keluarga bahwa tak ada yang salah denganmu kecuali sedikit tekanan saraf—hanya gejala histeris ringan—apa yang bisa kau perbuat?
Saudaraku juga seorang dokter, dan ia pun sepakat.
Jadi aku pun minum fosfat atau fosfit—aku bahkan lupa yang mana—juga tonik, bepergian, hirup udara segar, olahraga, dan sepenuhnya dilarang “bekerja” sampai aku sembuh.
Secara pribadi, aku tak sepakat dengan mereka.
Menurutku, pekerjaan yang menyenangkan, penuh gairah dan variasi, justru akan mempercepat kesembuhanku.
Tapi apa dayaku?
Aku sempat menulis diam-diam meski dilarang, tapi itu melelahkan sekali—terutama karena harus menyembunyikannya, atau menghadapi penolakan yang berat.
Kadang-kadang aku membayangkan, dalam keadaanku ini, andai aku mendapat dukungan alih-alih larangan, dan ditemani lebih banyak orang… Tapi John selalu berkata, hal paling buruk yang bisa kulakukan adalah terlalu memikirkan kondisiku, dan aku harus mengaku, setiap kali aku melakukannya, aku memang merasa lebih buruk.
Jadi sudahlah, aku akan membicarakan rumah ini saja.
Tempat ini sungguh indah! Berdiri sendiri, cukup jauh dari jalan utama, sekitar lima kilometer dari desa terdekat. Rumah ini mengingatkanku pada rumah-rumah Inggris dalam novel: pagar-pagar tanaman, tembok batu, gerbang-gerbang besi yang terkunci, dan banyak rumah kecil terpisah untuk para tukang kebun dan pelayan.
Taman di sini luar biasa! Aku belum pernah melihat taman seindah ini—luas dan teduh, dengan jalan setapak yang dibingkai tanaman boxwood, serta lorong anggur panjang beratap daun, lengkap dengan bangku-bangku di bawahnya.
Dulu ada rumah kaca juga, tapi semuanya sudah rusak.
Konon sempat ada masalah hukum—urusan warisan, begitu—makanya rumah ini kosong bertahun-tahun.
Hal itu memang merusak aura mistis yang kuharapkan, tapi aku tak peduli—ada sesuatu yang aneh di sini. Aku bisa merasakannya.
Aku pernah mengatakan ini pada John suatu malam saat bulan purnama, tapi ia malah berkata bahwa yang kurasa hanyalah angin malam, lalu menutup jendela.
Kadang aku jadi marah pada John tanpa alasan yang jelas. Aku rasa dulu aku tidak semudah ini tersinggung. Mungkin memang karena kondisiku.
Akan tetapi John bilang kalau aku terlalu mengikuti perasaan, aku akan kehilangan kendali diri. Jadi aku berusaha keras menjaga sikap—setidaknya di hadapannya—dan itu sungguh melelahkan.
Aku sama sekali tak suka kamar kami. Aku lebih ingin kamar di lantai bawah, yang jendelanya dipenuhi bunga mawar dan tirai chintz kuno yang manis. Tapi John menolak mentah-mentah.
Katanya, kamar itu hanya punya satu jendela, tak cukup untuk dua ranjang, dan tidak ada kamar yang cukup dekat jika ia ingin tidur terpisah.
John memang penuh perhatian dan sangat sayang padaku, nyaris tak mengizinkanku bergerak tanpa instruksi darinya.
Ia telah menyusun jadwal harian untukku. Ia menangani semua urusan agar aku bisa benar-benar beristirahat.
Katanya, kami datang ke sini semata-mata demi kesehatanku, agar aku bisa mendapat udara segar sebanyak mungkin. “Olahragamu tergantung kekuatanmu, sayang,” katanya, “dan makanmu tergantung selera. Tapi udara bisa kau hirup kapan pun.”
Jadi kami menempati kamar di loteng, bekas ruang bermain anak.
Kamar itu luas, nyaris seluas seluruh lantai atas, dengan jendela di segala arah, dipenuhi udara dan cahaya matahari. Aku rasa dulu kamar itu digunakan sebagai ruang bermain atau bahkan gym anak-anak; ada jeruji di jendelanya dan kait-kait serta lingkaran besi di dinding.
Cat dan kertas dindingnya tampak seperti sudah jadi korban satu sekolah anak laki-laki. Kertas dinding itu terkelupas besar-besaran di sekeliling tempat tidurku, sejauh jangkauanku, dan juga di sisi lain kamar dekat lantai.
Aku belum pernah melihat kertas dinding seburuk ini.
Motifnya besar-besar, berlebihan, dan mencoreng semua kaidah seni.
Terlalu membingungkan untuk diikuti dengan mata, terlalu menyolok untuk diabaikan, dan entah kenapa justru memancing untuk diamati. Namun begitu kau coba mengikuti garis-garisnya yang pincang, mereka tiba-tiba berbelok tajam tanpa arah, melenceng ke sudut-sudut ganjil, lalu membentur diri mereka sendiri dalam kekacauan yang mustahil dijelaskan.
Warnanya menjijikkan. Kuning kusam yang tampak kotor, seolah perlahan-lahan membusuk oleh sinar matahari.
Ada bagian yang seperti jingga pudar, di sisi lain tampak seperti belerang yang sakit.
Tak heran anak-anak membencinya. Aku pun akan membenci kamar ini jika harus tinggal lama di sini.
Ah, itu John datang. Aku harus segera menyimpan kertas ini—ia benci kalau aku menulis.
Dukung Penulis/Penerjemah Novel Favoritmu
Login untuk memberikan vote dukungan
💖 Suka baca cerita ini?
Bantu KlikNovel menerjemahkan lebih banyak novel public domain seperti The Yellow Wallpaper karya Charlotte Perkins Gilman ini. Scan QR Code untuk berdonasi via Saweria 🙏
📝 Belum ada komentar untuk bab ini. Jadilah yang pertama berkomentar!
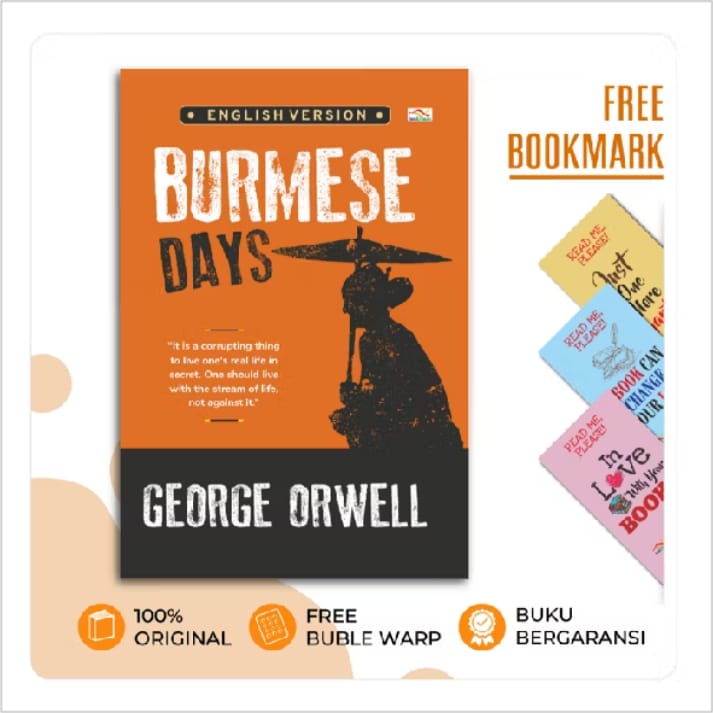


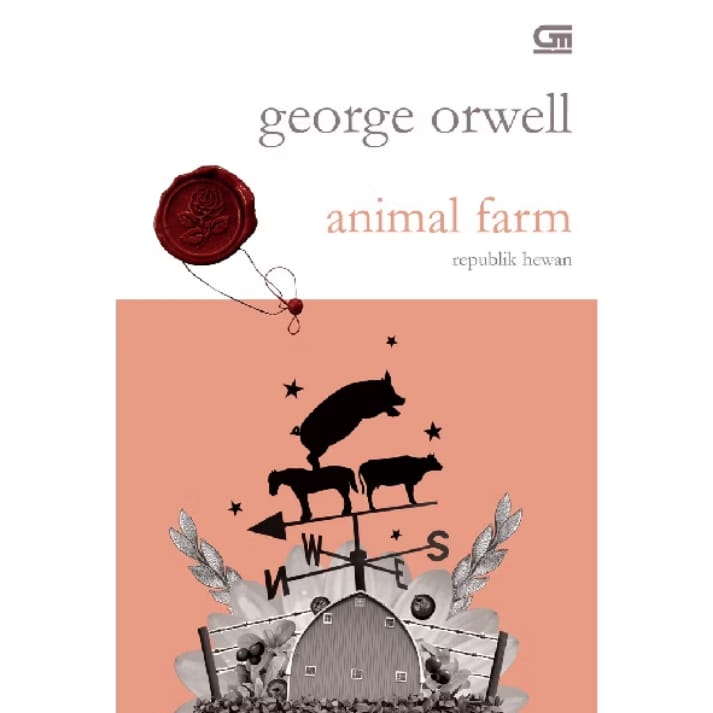



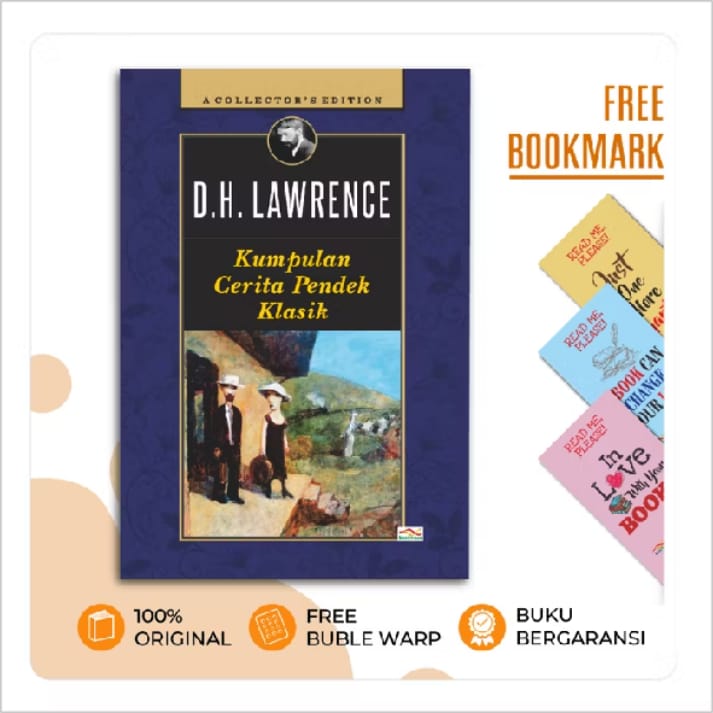
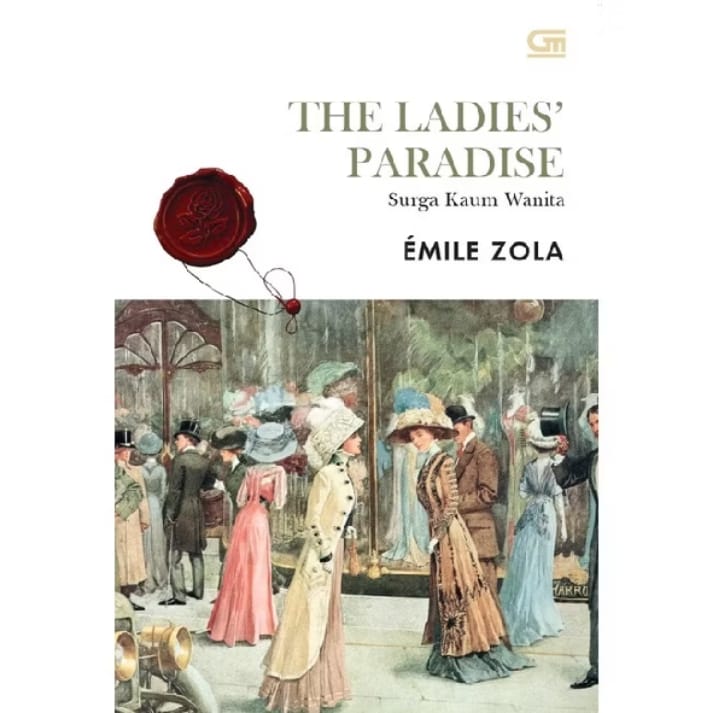

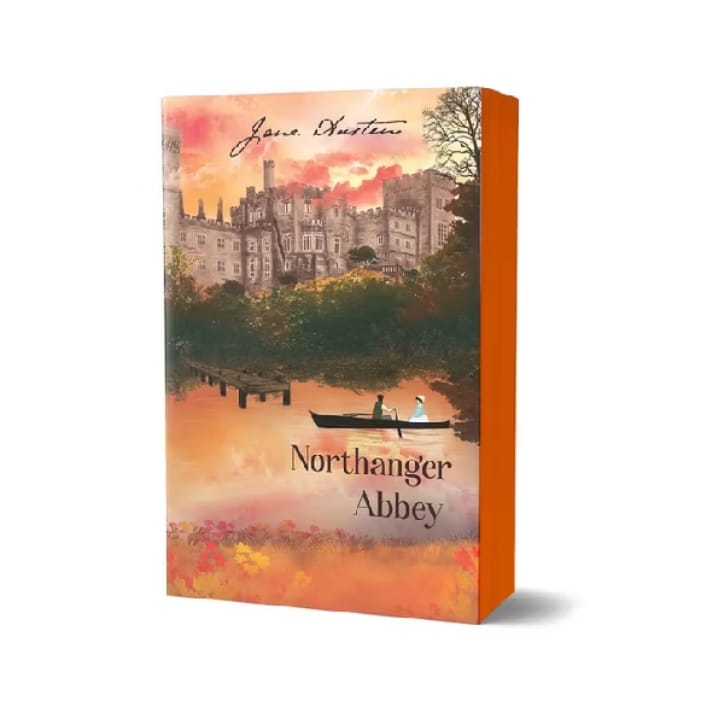
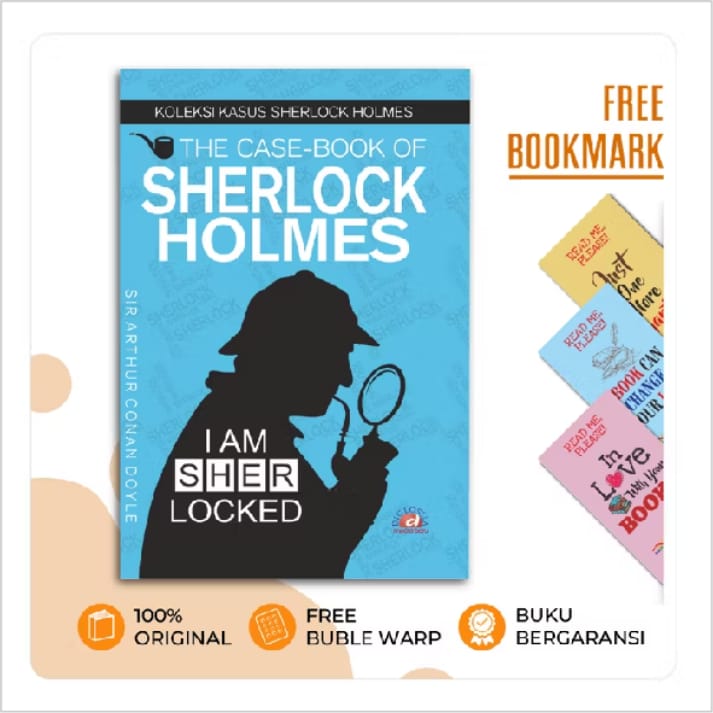
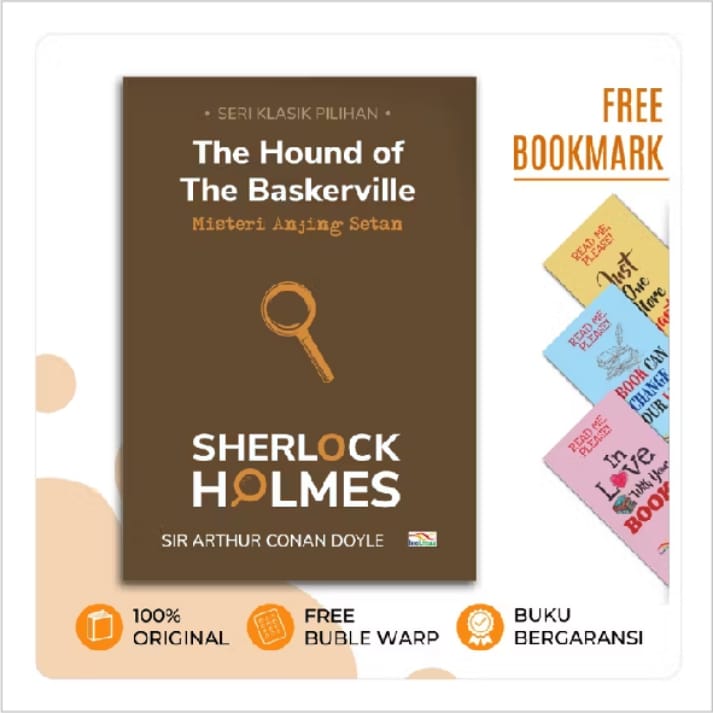



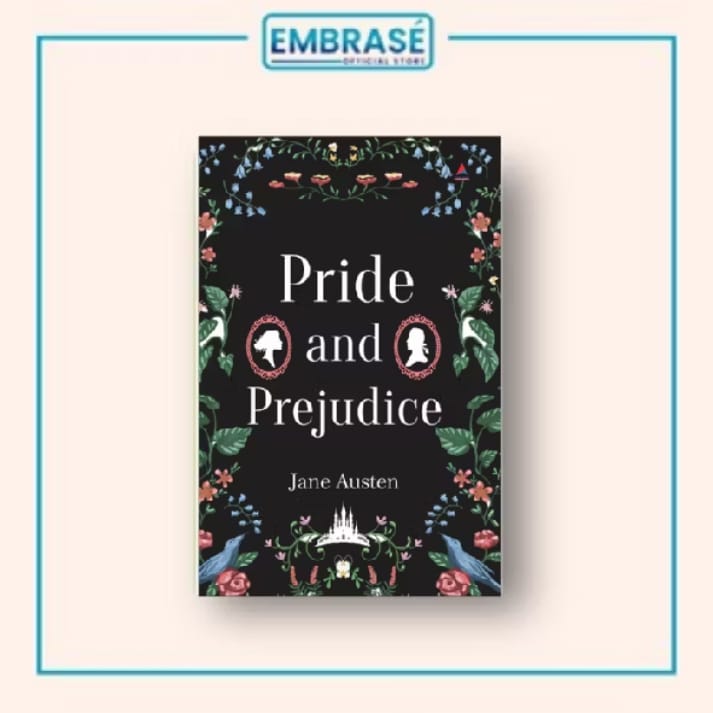
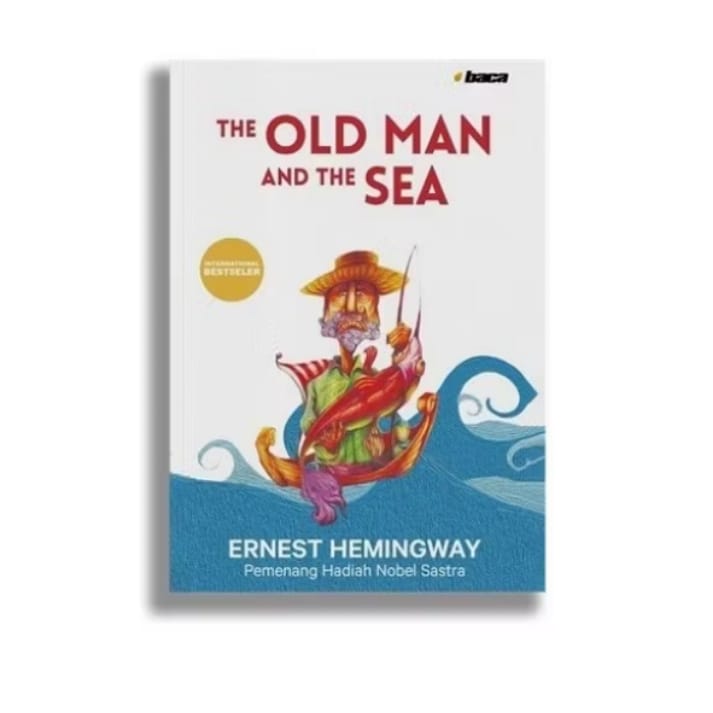
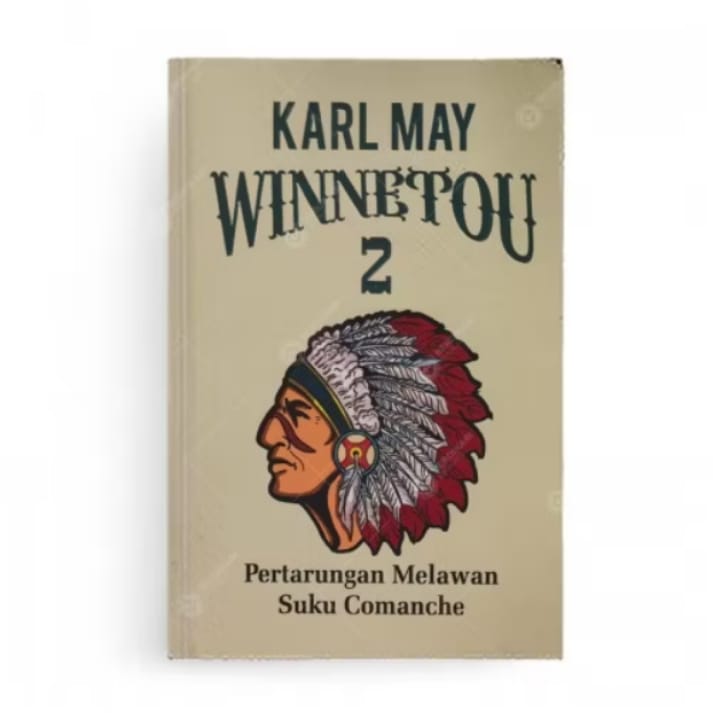

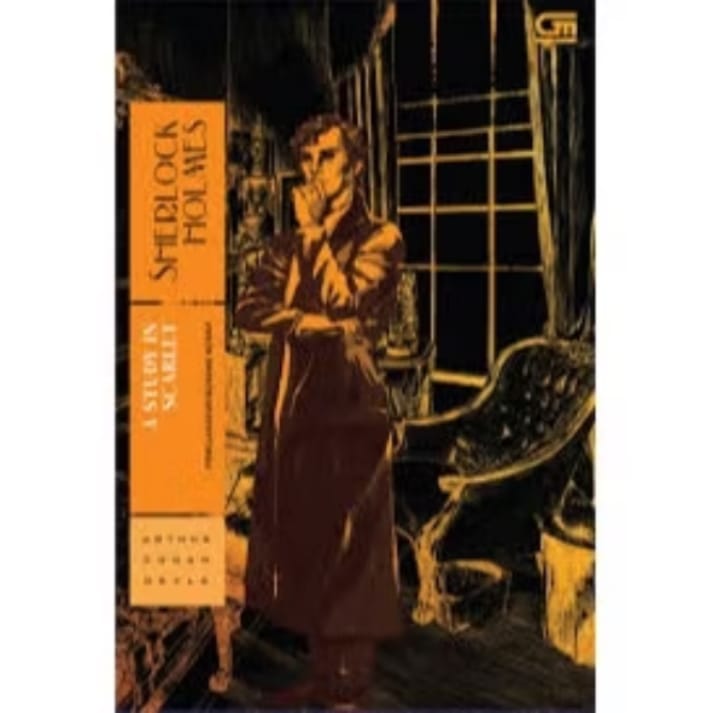
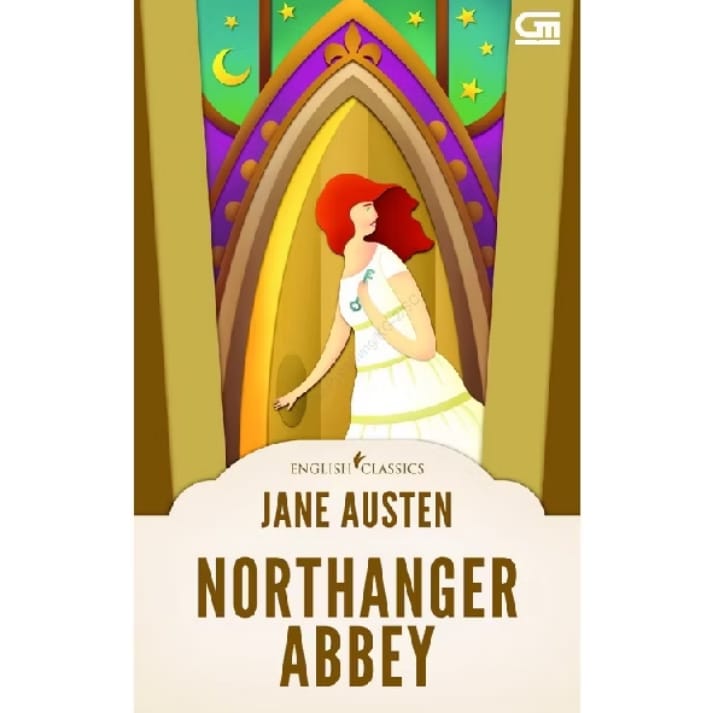
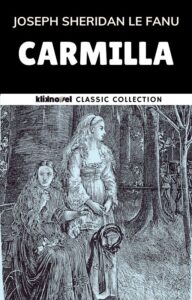
Silakan login untuk meninggalkan komentar.