Di Antara Gemerisik Daun Willow
Menerjemahkan The Willows adalah sebuah pengalaman yang sama memikat sekaligus melelahkan, karena karya ini berdiri di persimpangan antara keindahan sastra alam dan kengerian kosmik yang samar-samar.
Algernon Blackwood, yang lahir pada 1869, dikenal sebagai salah satu maestro cerita horor Edwardian. Namun The Willows menempati posisi yang istimewa: bukan sekadar cerita hantu, melainkan suatu upaya untuk menangkap rasa gentar manusia ketika berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih luas, dan lebih tidak terjangkau daripada dirinya.
H. P. Lovecraft bahkan menyebut karya ini sebagai “cerita horor supranatural terbaik sepanjang masa”—dan pernyataan itu, bagi siapa pun yang pernah membaca Lovecraft, tentu bukan pujian yang main-main.
Apa yang membuat The Willows berbeda dari kisah horor konvensional adalah cara Blackwood memusatkan teror bukan pada hantu, monster, atau darah, melainkan pada alam itu sendiri. Sungai Danube yang perkasa, dengan pulau-pulau willow yang seolah tak berujung, menjadi panggung sekaligus pelaku dalam cerita.
Kedua pengelana yang menjadi tokoh utama hanyalah tamu yang kebetulan singgah, dan perlahan mereka disadarkan bahwa kehadiran mereka tidak diinginkan. Embusan angin, gerak cabang willow, riak air, dan desiran malam bukan sekadar latar, melainkan bahasa dari sebuah eksistensi lain—sesuatu yang lebih besar daripada manusia, sesuatu yang bahkan tak peduli apakah manusia bisa mengerti atau tidak.
Dalam menerjemahkan novel ini, tantangan terbesar adalah menjaga atmosfer yang sangat subtil. Blackwood menggunakan kalimat-kalimat panjang, penuh deskripsi sensorik, yang menggiring pembaca ke dalam keadaan trans—antara kagum dan cemas.
Terjemahan yang terlalu kaku akan membunuh irama ini, tetapi terjemahan yang terlalu bebas juga bisa menghapus nuansa mencekam yang samar. Oleh sebab itu, saya memilih jalur tengah: mempertahankan kepuitisan Blackwood dengan bahasa Indonesia yang mengalir, tetapi tetap setia pada sugesti asli.
Misalnya, kata willows itu sendiri. Kata “pohon willow” dalam bahasa Indonesia tidak sepopuler di Eropa, tetapi kami tetap mempertahankannya, karena bunyi dan asosiasi “willow” sudah menjadi bagian integral dari atmosfer kisah ini.
Selain itu, Blackwood kerap bermain dengan ambiguitas. Apakah yang dialami para tokoh sungguh-sungguh hadir, atau sekadar ilusi yang lahir dari rasa lelah, lapar, dan keterasingan di alam liar?
Di sinilah kekuatan The Willows: ia tidak pernah memberi jawaban tegas. Alam tidak menjelaskan dirinya, dan manusia hanya bisa merasakan jejak samar dari sesuatu yang mungkin, atau mungkin juga tidak, eksis di luar nalar.
Dalam terjemahan ini, kami berusaha mempertahankan ruang kosong itu, membiarkan pembaca Indonesia pun turut mengisi dengan imajinasi mereka sendiri.
Mengapa The Willows layak hadir dalam bahasa Indonesia hari ini? Karena ia berbicara tentang hubungan manusia dengan alam dalam cara yang sangat relevan.
Di tengah krisis iklim dan kerusakan lingkungan, The Willows mengingatkan kita bahwa manusia bukanlah pusat, melainkan bagian kecil dari jagat raya yang jauh lebih besar dan misterius. Ada kekuatan yang tidak bisa dijinakkan, ada rahasia yang tidak bisa dipetakan.
Membaca kisah ini di abad ke-21 adalah sebuah peringatan sekaligus pengalaman estetik: bahwa ketakutan bisa lahir bukan hanya dari hantu, melainkan juga dari keagungan yang melampaui batas nalar manusia.
Kami berharap terjemahan ini dapat memberikan pengalaman serupa bagi pembaca Indonesia: rasa kagum yang bercampur gentar, rasa asing di tengah sesuatu yang begitu indah namun juga mengancam.
Jika setelah membaca, pembaca merasa seolah sedang mendengar bisikan dari balik dedaunan yang bergerak sendiri di malam hari, maka terjemahan ini telah berhasil menyampaikan apa yang dahulu dirancang Blackwood.
Dukung Penulis/Penerjemah Novel Favoritmu
Login untuk memberikan vote dukungan
📝 Belum ada komentar untuk bab ini. Jadilah yang pertama berkomentar!
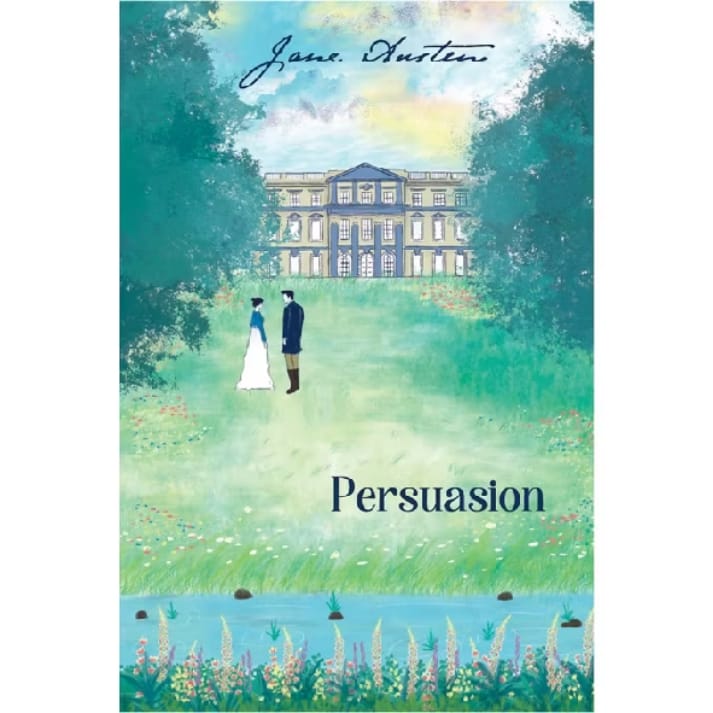

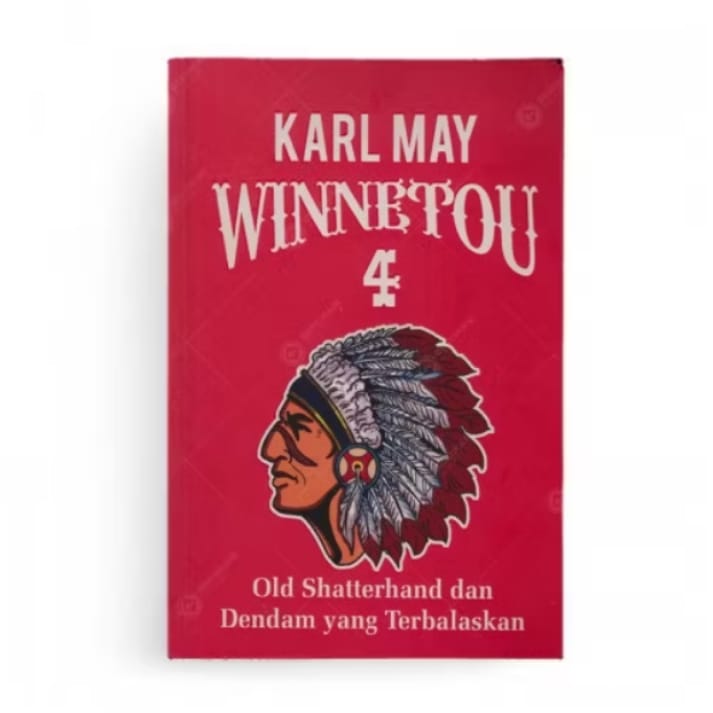
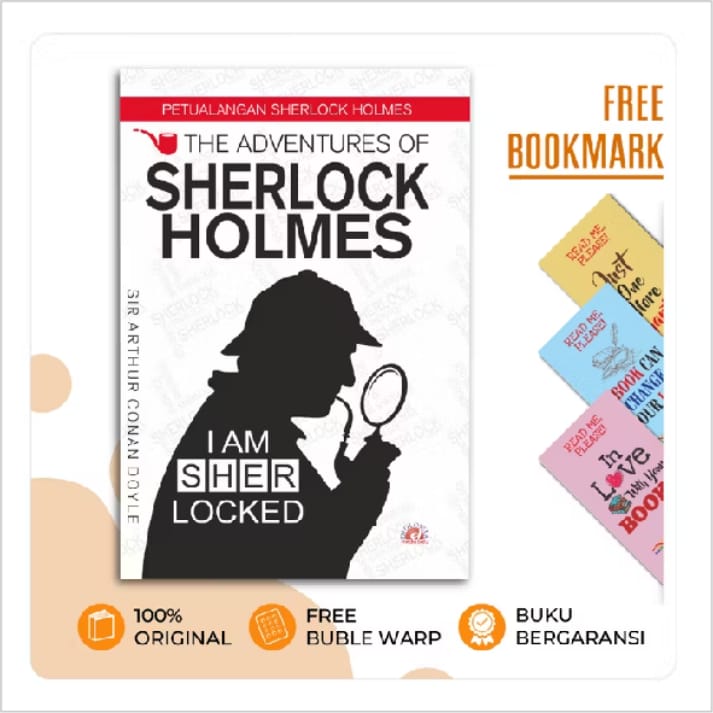
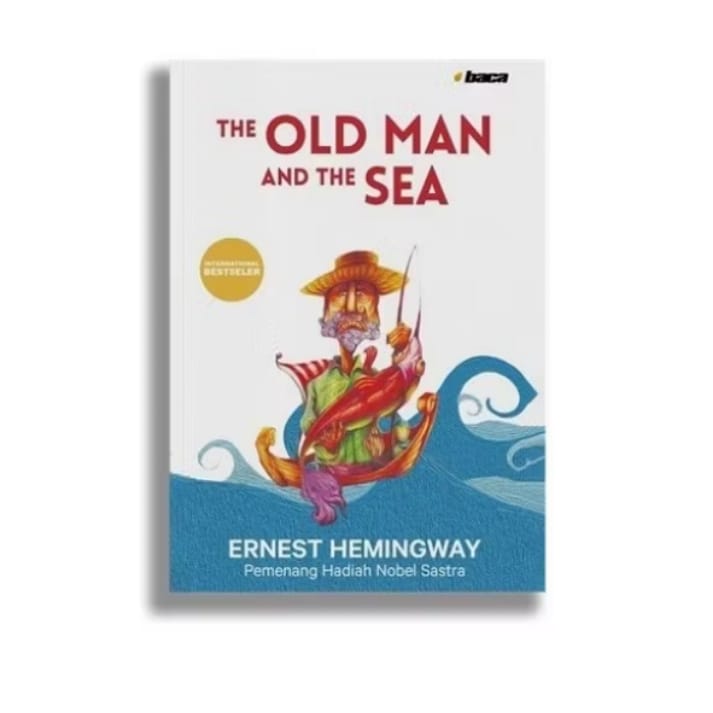
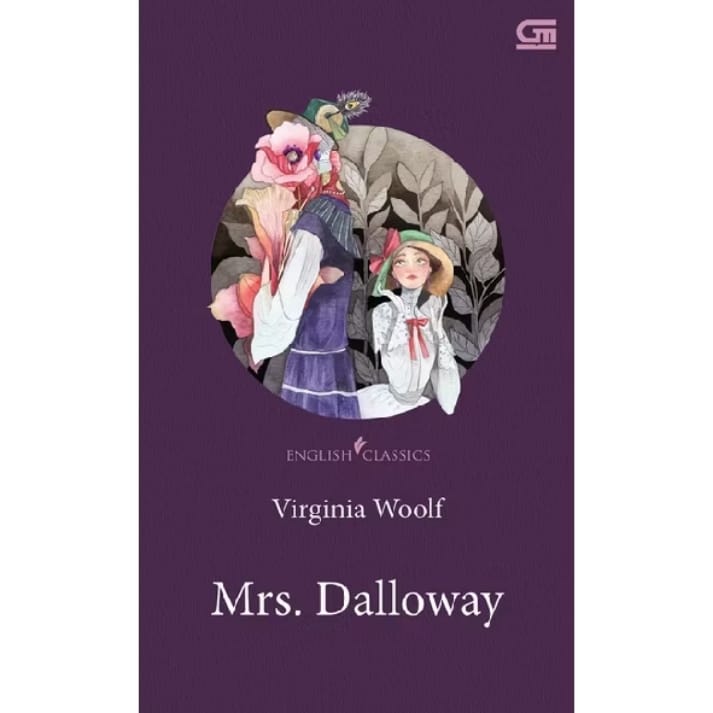


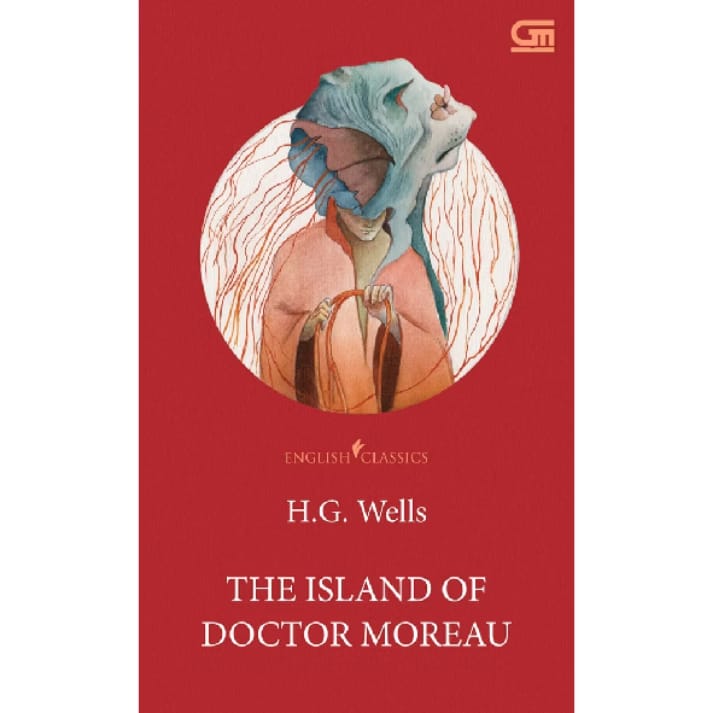

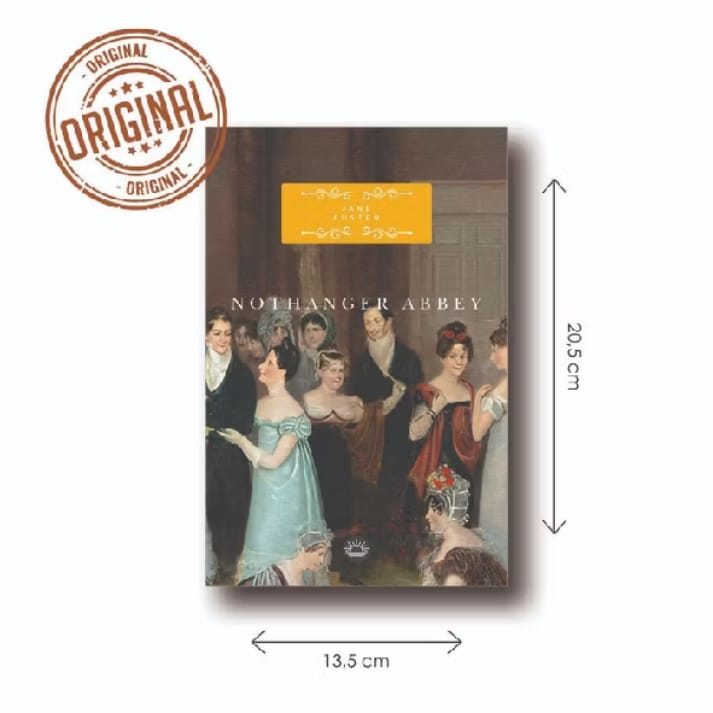
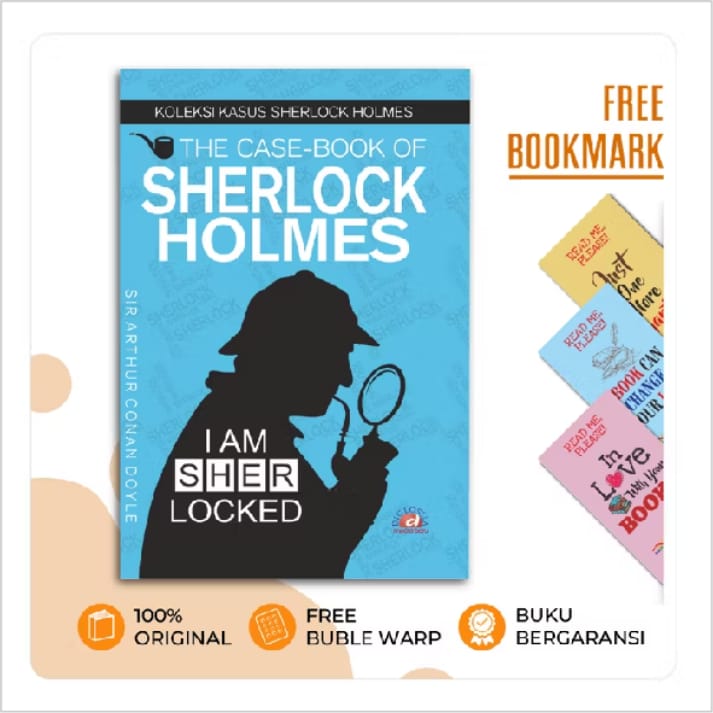
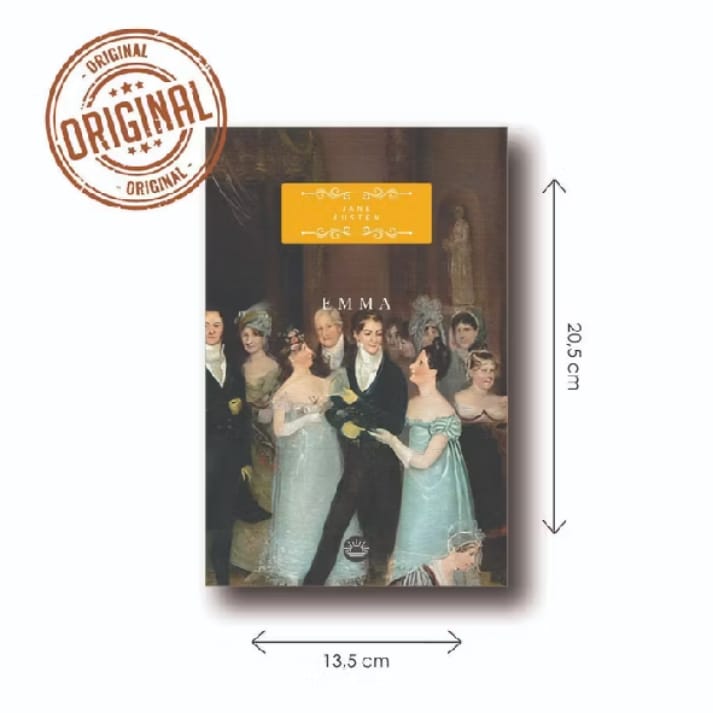
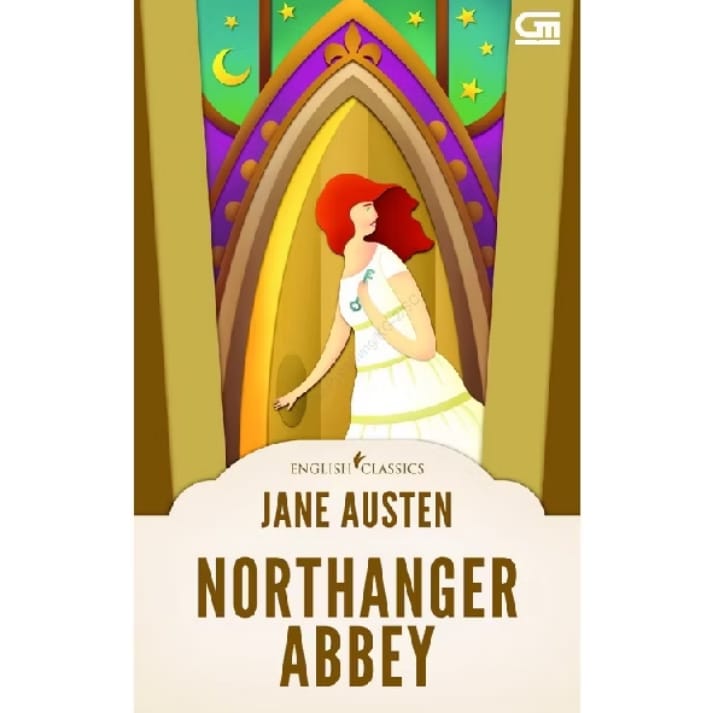


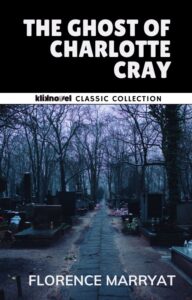
Silakan login untuk meninggalkan komentar.