Bab 1 — Ketakutan di Awal
DI Styria, kami—meskipun sama sekali bukan orang kaya—tinggal di sebuah kastel, atau schloss. Di daerah seperti ini, penghasilan kecil bisa terasa sangat cukup. Delapan atau sembilan ratus pound setahun mampu melakukan keajaiban. Kalau kami tinggal di tengah masyarakat yang lebih makmur, jumlah itu tentu terasa amat minim.
Ayahku orang Inggris, dan aku pun menyandang nama Inggris, meskipun aku sendiri belum pernah menginjakkan kaki di tanah Inggris. Namun di sini, di tempat terpencil dan sederhana ini, di mana segala sesuatu terasa begitu murah, aku sungguh tak yakin uang yang lebih banyak akan membuat hidup kami jadi jauh lebih nyaman—bahkan untuk hal-hal mewah sekalipun.
Ayah pernah bekerja dalam dinas militer Austria. Setelah pensiun, ia mengandalkan pensiunnya dan warisan keluarga, lalu membeli tempat tinggal kuno ini berikut tanah kecil di sekitarnya—semacam kesepakatan yang sangat menguntungkan waktu itu.
Sulit membayangkan tempat yang lebih indah dan lebih terpencil dari kastel kami. Ia berdiri di atas tanah sedikit tinggi, dikelilingi hutan. Jalan setapak kuno dan sempit melintas di depan jembatan gantung—yang selama hidupku tak pernah sekali pun diangkat—dan parit airnya dipenuhi ikan perch serta angsa-angsa putih yang berlayar di antara hamparan bunga teratai yang mengapung tenang di permukaan.
Dari seberang parit itu, tampak bagian depan schloss yang penuh jendela, lengkap dengan menara-menara serta kapel Gotik tua yang menghiasi bangunannya.
Hutan di depan gerbang terbuka menjadi lapangan kecil tak beraturan, tapi tampak indah. Di sisi kanan, sebuah jembatan batu gaya Gotik melintasi sungai kecil yang meliuk dalam bayangan rimbun pepohonan. Aku sudah bilang tempat ini sangat terpencil, bukan? Silakan nilai sendiri apakah aku melebih-lebihkan: jika kau berdiri di ambang pintu utama kastel dan memandang ke arah jalan, maka hutan tempat kami tinggal membentang sejauh 24 kilometer ke arah kanan, dan 19 kilometer ke kiri. Desa terdekat yang masih berpenghuni berjarak sekitar sebelas kilometer ke kiri.
Kastel berpenghuni terdekat yang punya nilai sejarah adalah milik General Spielsdorf yang sudah tua, terletak hampir tiga puluh dua kilometer jauhnya ke kanan.
Aku sebut “desa berpenghuni” karena tiga mil (sekitar lima kilometer) ke arah barat—yakni ke arah kastel General Spielsdorf—ada satu desa tua yang kini sudah menjadi reruntuhan. Di sana masih berdiri sebuah gereja mungil yang aneh, meskipun atapnya sudah hilang, dan di salah satu lorongnya terdapat makam tua keluarga bangsawan Karnstein, yang kini telah punah. Mereka dulu memiliki kastel terpencil yang sama sepinya, berdiri di tengah hutan, mengawasi puing-puing sunyi dari desa yang mereka tinggalkan.
Tentang alasan mengapa tempat yang begitu indah dan mencolok itu ditinggalkan hingga menjadi suram dan muram, ada sebuah legenda yang akan kuceritakan lain waktu.
Sekarang, izinkan aku menggambarkan betapa kecilnya jumlah penghuni tetap kastel kami. Aku tidak menghitung para pelayan dan orang-orang yang tinggal di bangunan tambahan di sekitar schloss. Dengarkan baik-baik, dan mungkin kau akan heran: Ayahku—yang merupakan orang paling baik di dunia, walaupun kini mulai menua—dan aku, yang saat cerita ini terjadi, baru berusia sembilan belas tahun. Kini delapan tahun sudah berlalu sejak masa itu.
Hanya kami berdua yang menjadi penghuni utama kastel. Ibuku, wanita asal Styria, meninggal saat aku masih bayi. Tapi aku diasuh oleh seorang pengasuh berhati baik yang sudah bersamaku nyaris seumur hidup. Aku bahkan tak ingat masa ketika wajah bulat dan ramahnya belum menjadi bagian dari ingatanku.
Namanya Madame Perrodon, asalnya dari Bern, Swiss. Ia baik hati dan penuh perhatian, dan entah bagaimana, ia menjadi semacam pengganti ibuku—seseorang yang tak bisa kuingat sama sekali karena kepergiannya terlalu awal. Madame Perrodon selalu menemani makan malam kecil kami.
Anggota keempat dalam lingkaran kecil ini adalah Mademoiselle De Lafontaine, seorang wanita yang mungkin akan kau sebut sebagai finishing governess—guru yang bertugas menyempurnakan pendidikan seorang gadis muda. Ia fasih berbahasa Prancis dan Jerman. Madame Perrodon bicara dalam bahasa Prancis dan bahasa Inggris yang patah-patah. Sementara aku dan ayahku berbicara dalam bahasa Inggris—baik sebagai upaya menjaga agar kami tak melupakan bahasa kami sendiri, maupun sebagai bentuk rasa cinta tanah air. Hasilnya? Percakapan kami di rumah jadi seperti menara Babel mini yang cukup membuat orang luar tertawa. Tapi jangan khawatir, aku tak akan berusaha menirukan kekacauan itu dalam kisah ini.
Selain itu, ada dua atau tiga teman perempuan seusia denganku yang sesekali datang berkunjung, kadang hanya sebentar, kadang agak lama. Aku pun kadang membalas kunjungan mereka.
Itulah lingkup sosial kami sehari-hari. Tentu saja ada juga kunjungan acak dari para “tetangga”—yang jaraknya bisa mencapai lima atau enam liga jauhnya. Tapi tetap saja, hidupku cenderung sepi. Aku benar-benar bisa meyakinkanmu soal itu.
Para gouvernante (pengasuh dan guru privat) itu punya kendali secukupnya atasku—sebatas yang mungkin kau duga jika membayangkan seorang gadis muda yang agak dimanja dan satu-satunya anak dari ayah yang membiarkannya melakukan hampir semua hal sesuai kehendaknya sendiri.
Peristiwa pertama dalam hidupku yang menorehkan kesan mengerikan—dan sampai sekarang belum pernah benar-benar terhapus dari pikiranku—adalah salah satu kenangan paling awal yang bisa kuingat.
Sebagian orang mungkin menganggap kejadian ini sepele dan tak layak diceritakan. Tapi nanti kamu akan paham kenapa aku tetap memilih untuk menceritakannya.
Waktu itu, aku masih sangat kecil, tak lebih dari enam tahun. Ruanganku—yang disebut sebagai kamar bayi, meski aku satu-satunya penghuninya—adalah kamar luas di lantai atas kastel, beratapkan kayu ek yang curam.
Suatu malam, aku terbangun. Aku menoleh ke sekeliling tempat tidur dan menyadari bahwa pengasuhku tidak ada. Begitu pula perawat malamku. Aku merasa sendirian. Tapi aku tidak ketakutan. Aku termasuk anak yang cukup beruntung karena dibesarkan tanpa cerita hantu, dongeng menakutkan, atau kisah menyeramkan lainnya yang bisa membuat anak kecil menjerit hanya karena suara pintu berderit atau bayangan aneh di dinding.
Tapi aku merasa kesal. Merasa diabaikan. Dan seperti anak kecil yang mulai ngambek, aku mulai merengek—pemanasan sebelum menangis sekencang-kencangnya. Tapi sebelum aku sempat benar-benar menjerit, aku melihat sesuatu yang mengejutkan: sebuah wajah cantik namun serius menatapku dari sisi tempat tidur.
Itu wajah seorang perempuan muda yang sedang berlutut, tangannya berada di bawah selimut. Aku menatapnya dengan rasa heran yang aneh tapi menyenangkan, dan tangisku pun berhenti. Ia mengelusku dengan lembut, lalu berbaring di sebelahku dan memelukku sambil tersenyum. Aku langsung merasa tenang luar biasa, dan tertidur kembali.
Tapi aku terbangun tak lama kemudian karena merasakan sensasi aneh—seperti dua jarum tajam yang menancap dalam ke dadaku pada saat yang sama. Aku berteriak kencang.
Perempuan itu terkejut dan mundur, matanya menatapku tajam, lalu menghilang begitu saja ke bawah tempat tidur—begitu menurut dugaanku saat itu.
Saat itulah, untuk pertama kalinya, aku benar-benar ketakutan. Aku menjerit sekeras mungkin. Pengasuh, perawat malam, dan kepala rumah tangga semua berlari masuk. Saat aku menceritakan apa yang terjadi, mereka mencoba menenangkanku, tapi aku tahu dari wajah mereka bahwa mereka tidak benar-benar tenang. Wajah mereka pucat, ada kegelisahan yang mereka coba sembunyikan. Mereka memeriksa ke bawah tempat tidur, memeriksa setiap sudut kamar, bahkan membuka lemari dan memeriksa kolong meja.
Kepala rumah tangga berbisik kepada pengasuh, “Letakkan tanganmu di lekukan kasur itu; ada yang memang berbaring di sana. Tempatnya masih hangat.”
Aku masih ingat bagaimana perawat malam mencoba membujukku sambil memeriksa dadaku—tempat aku bilang merasakan tusukan. Mereka tidak menemukan bekas apa pun. Tak ada luka, tak ada tanda.
Sejak malam itu, kepala rumah tangga dan dua pengasuh selalu berjaga di kamar sepanjang malam, dan kebiasaan itu bertahan sampai aku berusia sekitar empat belas tahun.
Setelah kejadian itu, aku menjadi sangat penakut. Seorang dokter tua dipanggil. Ia pucat, wajahnya panjang dan serius, dengan bekas cacar yang samar, dan mengenakan wig kastanye. Aku masih ingat jelas wajahnya. Selama beberapa minggu, ia datang dua hari sekali memberiku obat—yang tentu saja sangat kubenci.
Keesokan paginya setelah “penampakan” itu, aku masih sangat ketakutan. Bahkan saat matahari sudah tinggi, aku tak mau ditinggal sendirian walau sebentar.
Ayah datang menjenguk, berdiri di samping tempat tidur, mencoba menghiburku sambil berbicara ceria dan menanyakan banyak hal kepada pengasuh. Ia tertawa keras mendengar salah satu jawabannya, lalu menepuk pundakku, menciumku, dan berkata aku tak perlu takut. “Itu cuma mimpi,” katanya. “Tak akan menyakitimu.”
Tapi aku tidak terhibur. Karena aku tahu—sungguh tahu—bahwa kunjungan perempuan asing itu bukan mimpi. Dan aku sangat… sangat ketakutan.
Sedikit hiburan kudapat dari perawat malam, yang meyakinkan bahwa dialah yang datang dan berbaring di sampingku. Katanya, aku pasti setengah tertidur hingga wajahnya tampak asing bagiku. Pengasuh mendukung cerita itu. Tapi… tetap saja aku tidak sepenuhnya percaya.
Hari itu juga, aku ingat seorang pria tua berpakaian hitam—mungkin seorang pendeta—datang bersama pengasuh dan kepala rumah tangga. Ia berbicara pelan kepada mereka, dan ramah sekali padaku. Wajahnya sangat lembut dan penuh kasih. Ia bilang mereka akan berdoa, lalu menyatukan kedua tanganku dan memintaku mengucapkan, pelan-pelan, “Tuhan, dengarlah semua doa yang baik untuk kami, demi Yesus.” Seingatku, itulah kata-kata persisnya. Aku sering mengulanginya dalam doa selama bertahun-tahun, dan perawatku pun selalu menyuruhku mengucapkannya.
Aku masih bisa membayangkan wajah tua penuh kasih itu, rambutnya putih, berdiri di kamar besar dan tua yang tinggi, dengan perabot kuno berumur ratusan tahun, dan cahaya tipis yang masuk lewat jendela kecil. Ia berlutut, begitu juga tiga perempuan yang bersamanya, dan ia berdoa dengan suara bergetar, lama dan sungguh-sungguh.
Aku lupa segalanya tentang hidupku sebelum peristiwa itu. Bahkan beberapa waktu setelahnya juga masih samar. Tapi apa yang baru saja kuceritakan—semua adegan ini—terpahat jelas dalam benakku, seperti gambar-gambar terang di layar phantasmagoria yang muncul sejenak lalu hilang dalam kegelapan.
Dukung Penulis/Penerjemah Novel Favoritmu
Login untuk memberikan vote dukungan
💖 Suka baca cerita ini?
Bantu KlikNovel menerjemahkan lebih banyak novel public domain seperti Carmilla karya Joseph Sheridan Le Fanu ini. Scan QR Code untuk berdonasi via Saweria 🙏
📝 Belum ada komentar untuk bab ini. Jadilah yang pertama berkomentar!


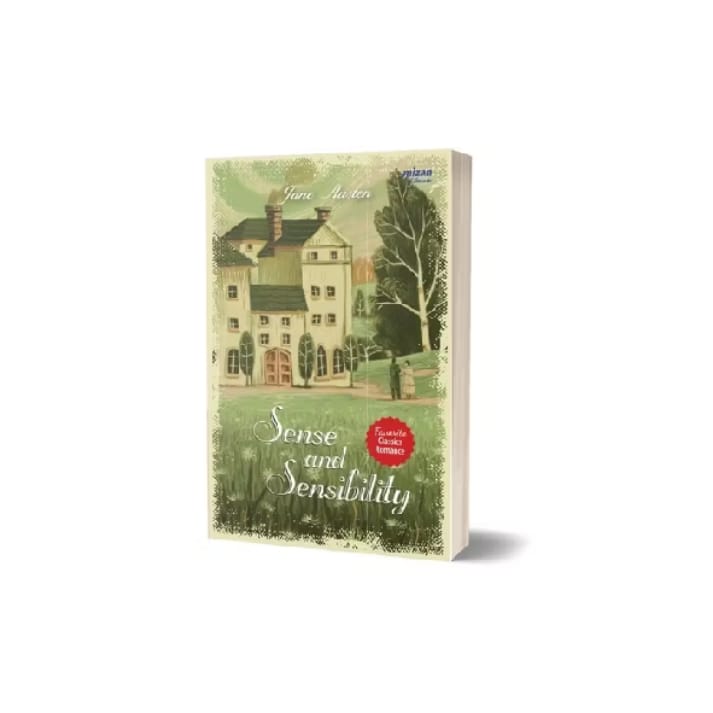


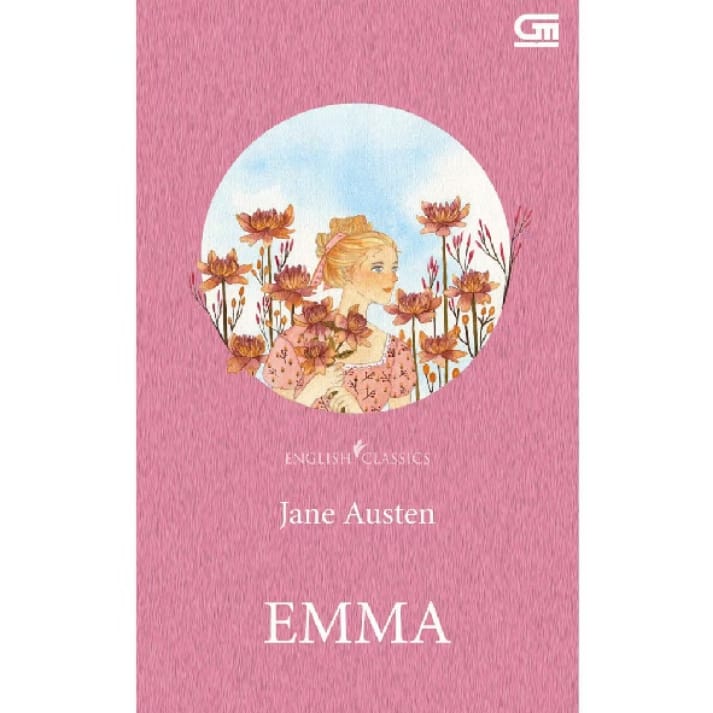
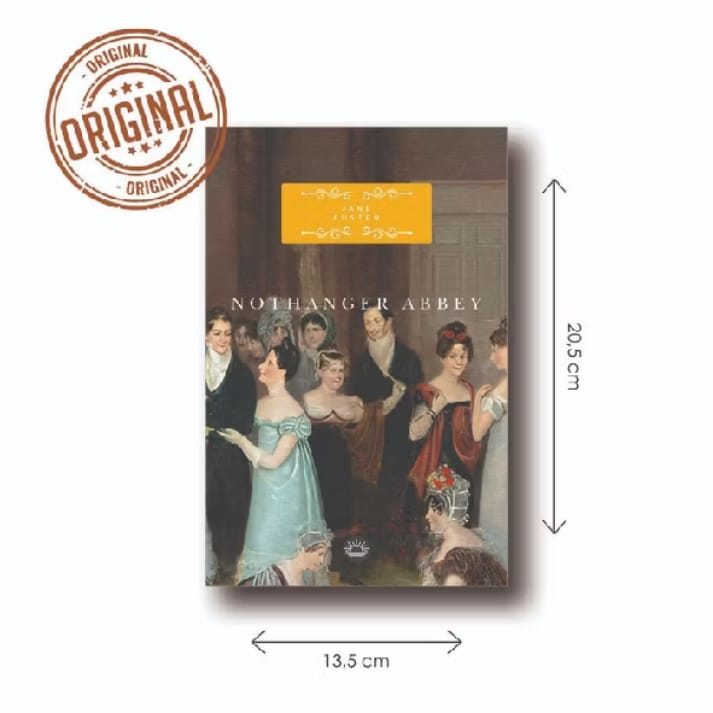

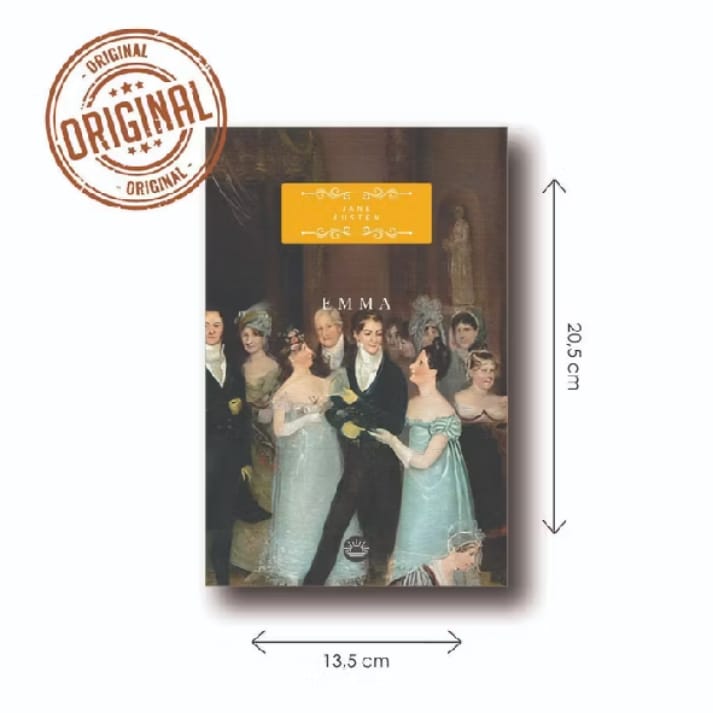

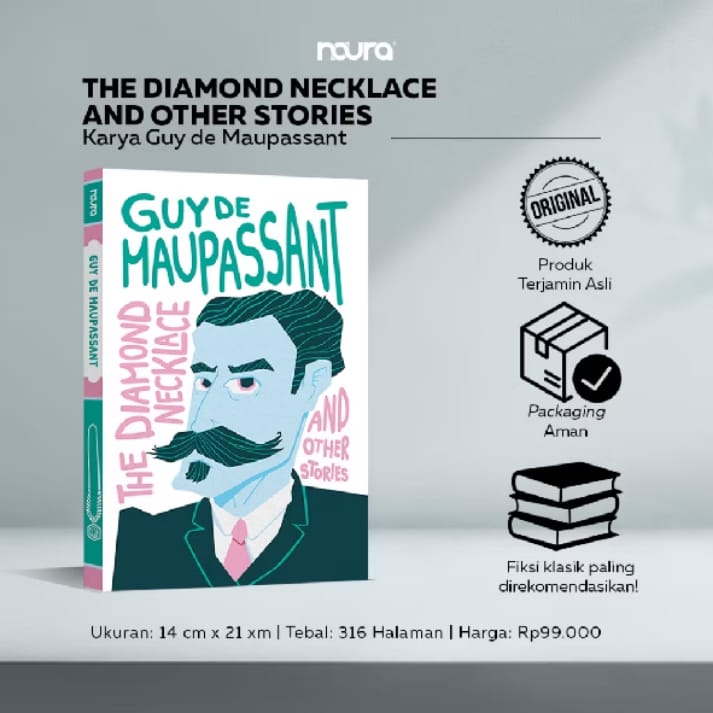



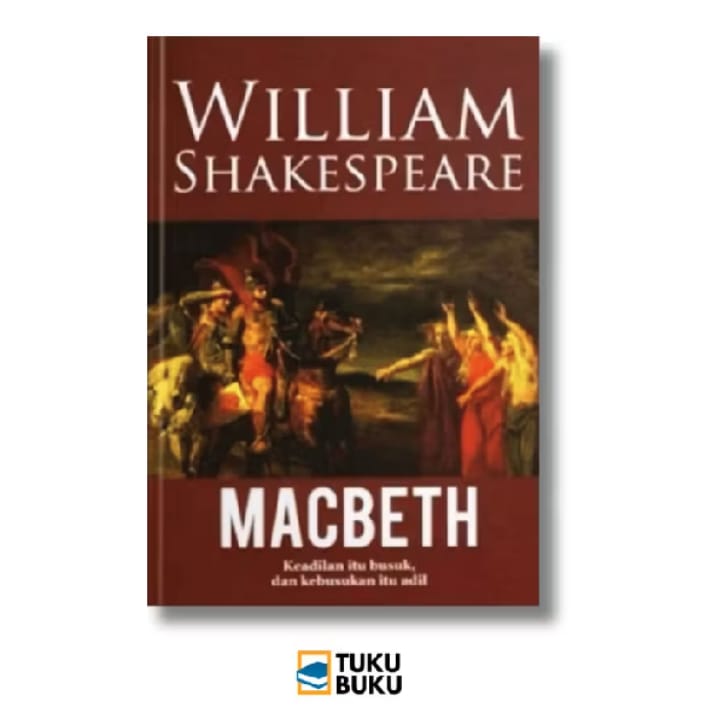

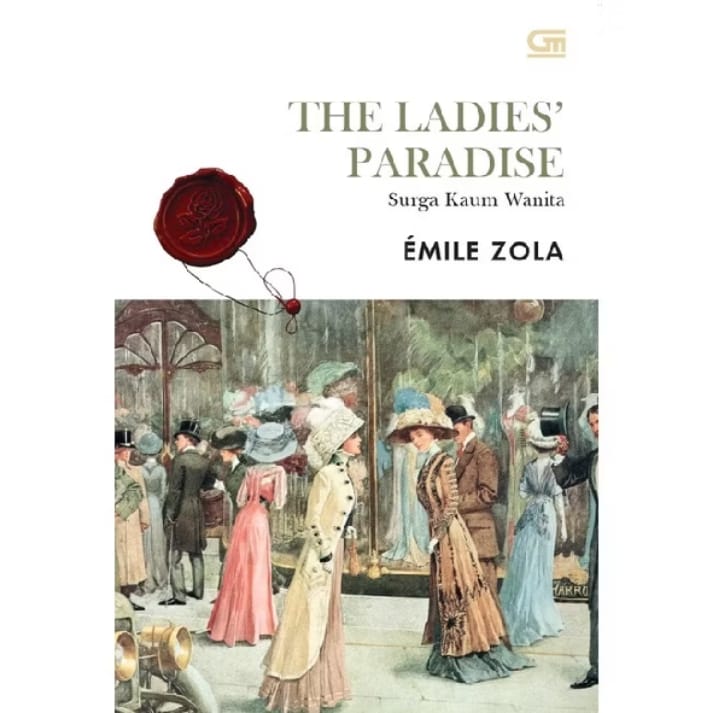

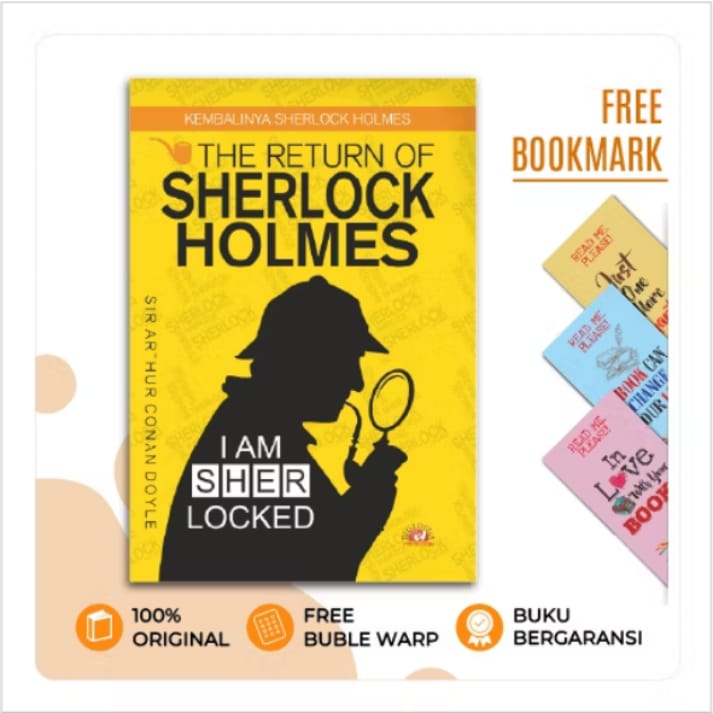
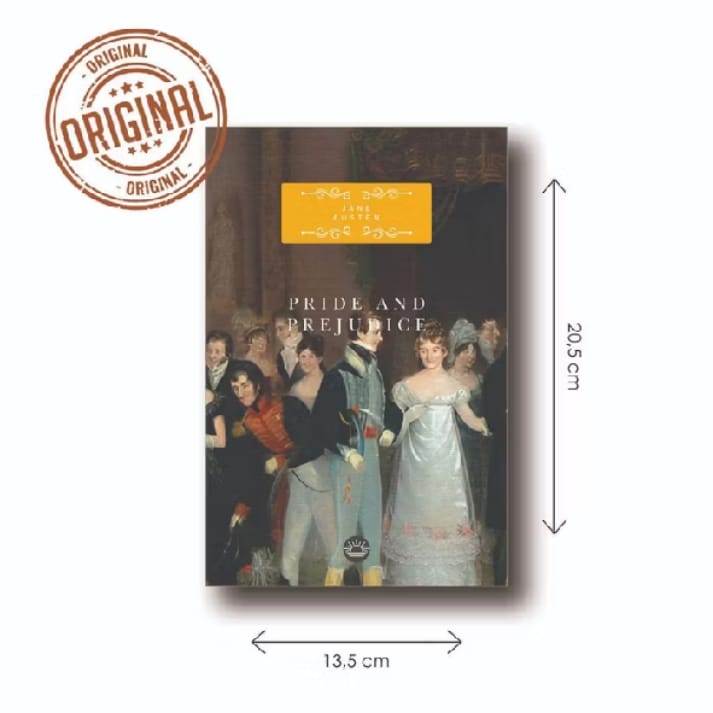
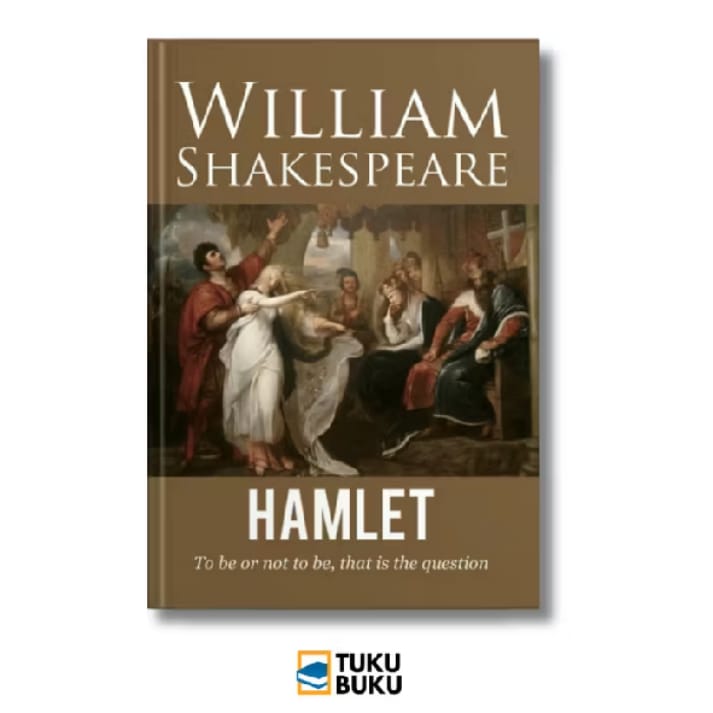

Silakan login untuk meninggalkan komentar.