Bagian 2 — Kepergian di Bawah Siraman Salju
SETELAH pasukan Prusia benar-benar mengendalikan kota dengan disiplin baja mereka—tanpa kekejaman yang sebelumnya menodai jejak kemenangan mereka di tempat lain—rasa takut perlahan memudar. Perdagangan kembali menggeliat, sebab orang-orang kaya punya kepentingan yang harus diselamatkan.
Beberapa di antara mereka punya bisnis besar di Havre, yang masih dikuasai tentara Prancis. Maka mereka pun menyusun rencana: pergi ke Dieppe lewat darat, lalu menyeberang dengan kapal.
Dengan segala koneksi dan basa-basi yang telah mereka bangun bersama perwira Prusia, akhirnya surat izin keberangkatan pun dikantongi—resmi, cap komandan tertinggi.
Sebuah kereta besar ditarik empat kuda dipesan khusus untuk perjalanan ini. Sepuluh orang mendaftar untuk ikut serta. Mereka sepakat berangkat Selasa pagi, sebelum fajar menyingsing—agar tak terlalu jadi sorotan.
Sehari sebelumnya, bumi telah membeku. Dan menjelang pukul tiga sore, awan hitam bergulung dari utara, lalu salju turun tanpa henti. Malam itu, kota terbungkus sunyi putih yang lembut namun menggigilkan.
Pukul setengah lima pagi, para penumpang mulai berkumpul di halaman Hôtel Normandie. Mereka masih setengah tertidur, membungkus diri dengan syal dan mantel tebal, menggigil menahan dingin.
Dalam remang dini hari yang berat dan bisu, mereka nyaris tak saling mengenali. Lapisan kain musim dingin membuat mereka terlihat seperti pendeta gendut dalam jubah panjang.
Dari sepuluh orang, hanya dua pria yang saling kenal. Seorang ketiga menghampiri dan bergabung dalam obrolan ringan.
“Aku membawa istriku,” kata yang satu.
“Aku juga,” timpal yang lain.
“Sama, aku pun begitu,” ujar yang ketiga.
Si pertama menambahkan, “Kami tak akan kembali ke Rouen. Kalau Prusia juga mendekati Havre, kami akan terus ke Inggris.”
Rupanya, mereka semua punya rencana serupa—dan satu suara dalam hati maupun pikiran.
Sementara itu, kuda-kuda belum juga dipasangi pelana. Seorang anak kandang muncul dan hilang bergantian lewat pintu yang berbeda, membawa lentera kecil yang menyala redup.
Terdengar suara kaki kuda mengentak-entak lantai—teredam jerami dan sekam. Dari sudut kandang, terdengar suara pria bercakap dengan hewan-hewan itu, kadang dengan kata-kata kasar.
Bunyi gemerincing lonceng mulai terdengar lirih, lalu semakin ritmis ketika pelana mulai dipasang—dengan sesekali hentakan mendadak, disusul ketukan sepatu kayu di lantai beku.
Lalu, pintu besar ditutup rapat. Suara-suara lenyap. Warga kota yang membeku dalam diam tetap berdiri kaku, seolah menjadi bagian dari patung salju yang perlahan terbentuk.
Tirai serpihan putih turun tiada henti dari langit, menghapus garis bentuk dan membungkus segalanya dalam selimut halus seperti lumut lembut. Tak ada suara. Kota tertidur dalam diam yang nyaris suci.
Hanya salju yang turun. Bukan suara, melainkan perasaan. Partikel-partikel kecil bergetar di udara, tak terdengar namun memenuhi ruang.
Tak lama, laki-laki dengan lentera kembali, menarik seekor kuda kusam yang enggan berjalan. Ia memasang tali pada poros kereta, mengikat tali kekang dengan satu tangan, sementara tangan satunya tetap memegang cahaya.
Saat kembali mengambil kuda kedua, ia melirik para penumpang yang berdiri mematung, tubuh mereka mulai memutih tertutup salju.
“Mengapa kalian tak masuk saja ke dalam?” katanya, datar. “Setidaknya kalian bisa berlindung.”
Mereka semua tampak tersadar, seolah baru mengingat kereta yang berdiri di depan mereka. Bergegas, tiga pria membantu istri masing-masing naik ke tempat duduk belakang, lalu menyusul masuk. Sosok-sosok lain, samar dan ragu, menaiki kursi yang tersisa tanpa sepatah kata.
Lantai kereta dilapisi jerami. Kaki mereka tenggelam dalam hangat yang semu.
Para wanita di bagian belakang membawa pemanas kaki tembaga kecil, dengan bara menyala di dalamnya. Mereka pun menyalakan alat-alat itu, lalu mulai berbisik—membandingkan kehangatan, mengulang-ulang manfaat benda yang sudah mereka kenal sejak lama.
Akhirnya, kereta ditarik bukan oleh empat, melainkan enam ekor kuda. Jalanan terlalu buruk untuk setengah hati.
Seseorang berseru dari luar, “Semua sudah naik?”
Dan dari dalam, sebuah suara menjawab pelan, “Sudah.”
Mereka pun berangkat. Kereta mulai bergerak perlahan, nyaris enggan meninggalkan tempatnya. Roda-roda terperosok dalam salju yang tebal; seluruh badan kereta berderit berat, seolah-olah mengeluh; kuda-kuda berkilau oleh keringat, terengah-engah, mengepulkan uap dari moncongnya; dan cambuk sang kusir tak henti-hentinya berdesing di udara, melayang ke segala arah, melingkar dan meletup seperti ular tipis yang menyambar, menghantam punggung seekor kuda yang sedang berayun, membuatnya mencurahkan segenap tenaganya.
Cahaya pagi mulai menyelinap perlahan—hampir tak terasa. Butiran halus salju yang, menurut salah satu penumpang asal Rouen, mirip kapas yang beterbangan, kini tak lagi turun. Sinar lembut menembus awan kelabu yang muram, membuat putihnya ladang tampak semakin mencolok.
Di kejauhan, garis pepohonan besar berdiri diam dalam balutan salju; sesekali terlihat cerobong asap beratap putih.
Dukung Penulis/Penerjemah Novel Favoritmu
Login untuk memberikan vote dukungan
💖 Suka baca cerita ini?
Bantu KlikNovel menerjemahkan lebih banyak novel public domain seperti Boule de Suif karya Guy de Maupassant ini. Scan QR Code untuk berdonasi via Saweria 🙏
📝 Belum ada komentar untuk bab ini. Jadilah yang pertama berkomentar!

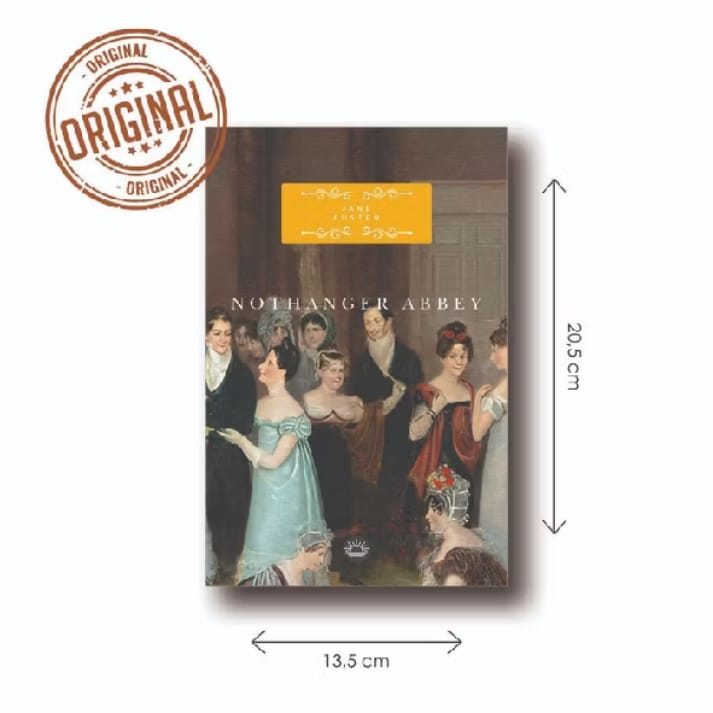
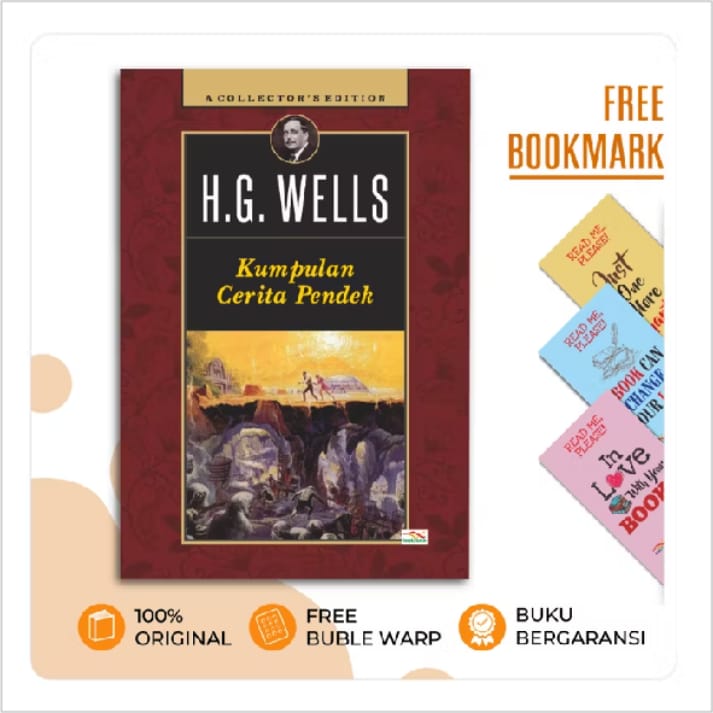
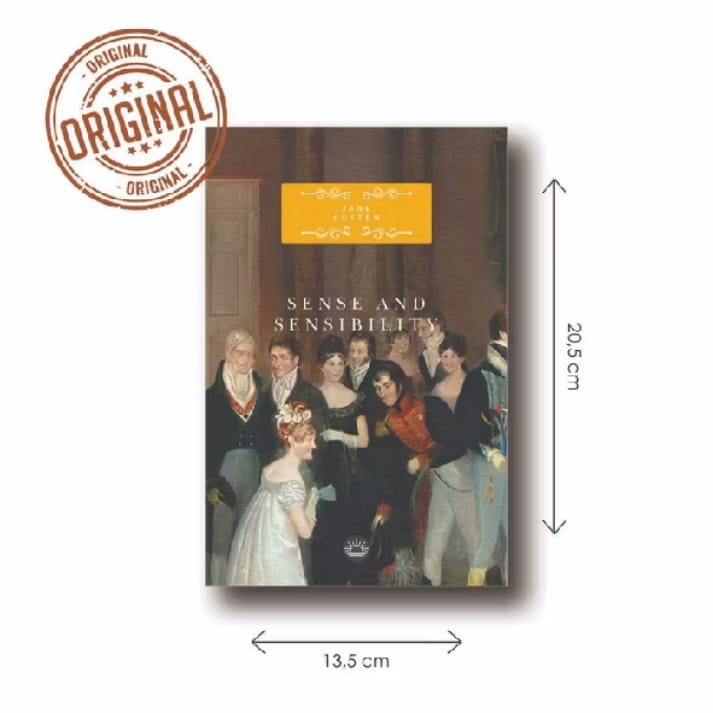


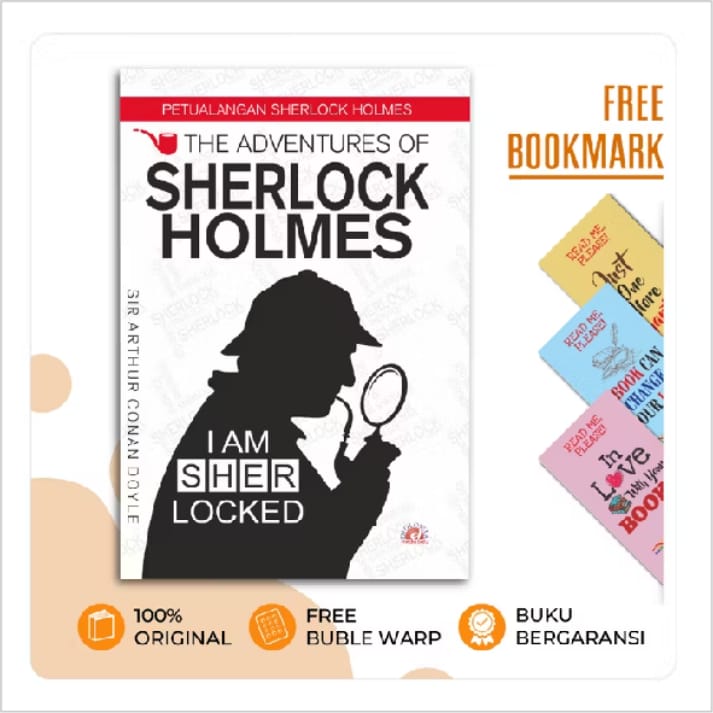

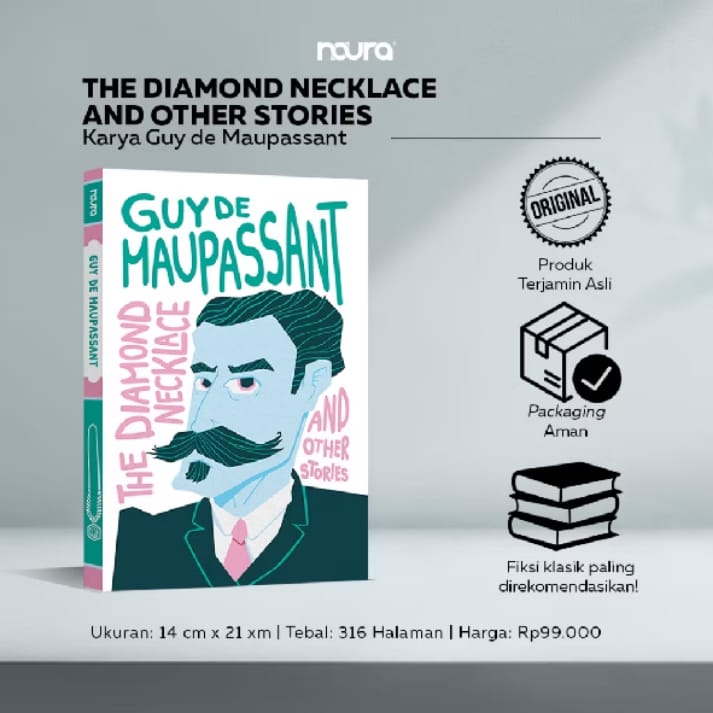
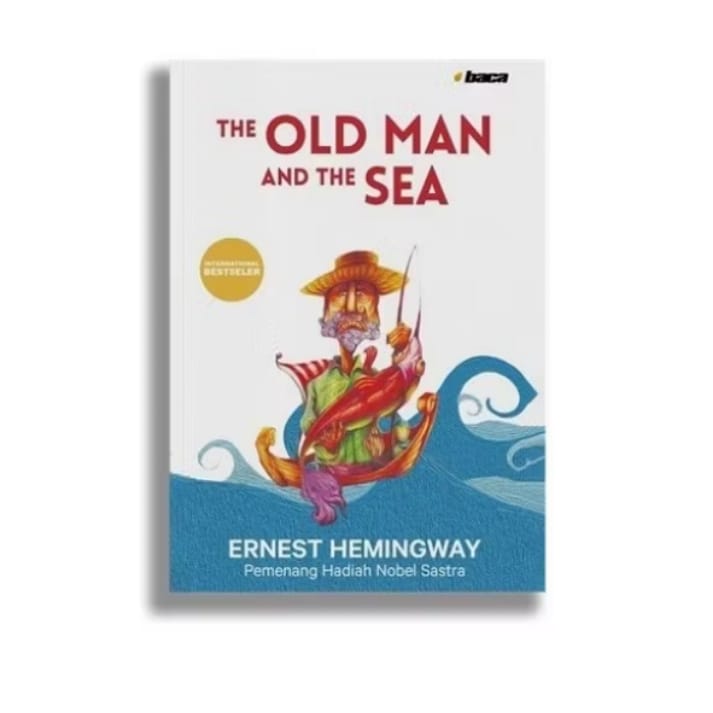
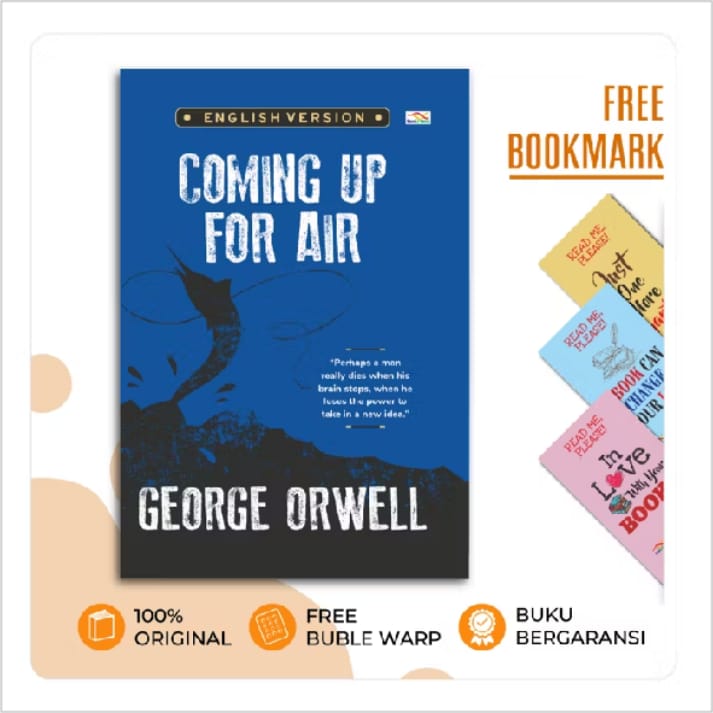


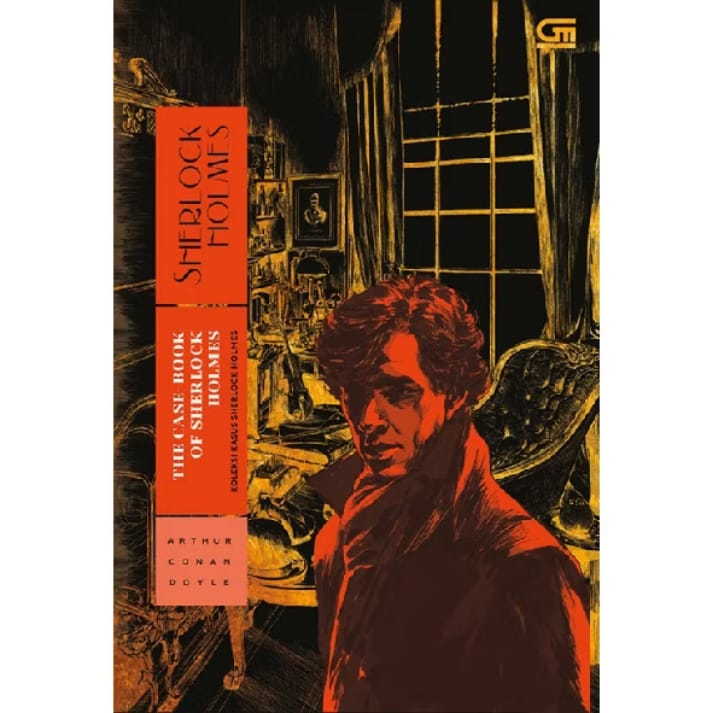


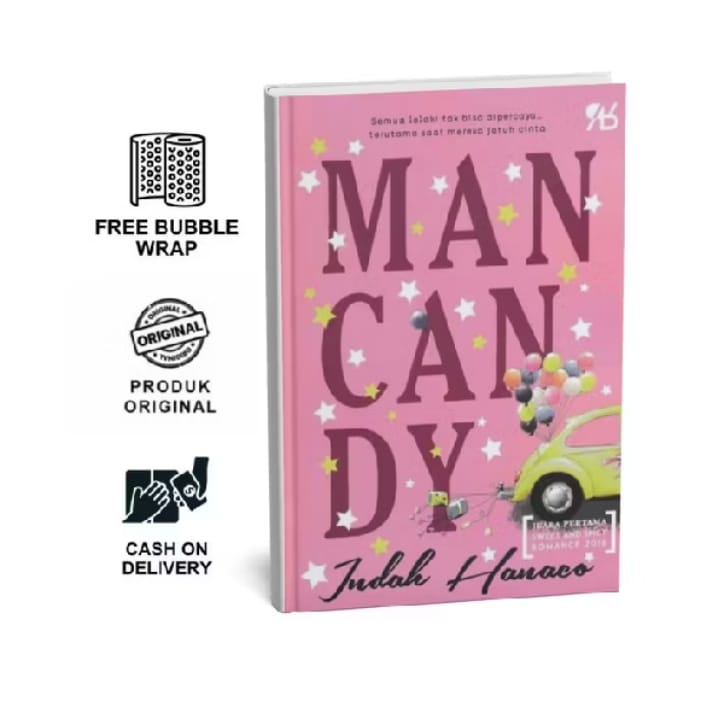



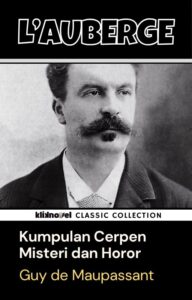
Silakan login untuk meninggalkan komentar.