Ketegangan yang Kian Mencekik
CERITA itu membuat kami semua terdiam di sekitar perapian, menahan napas. Namun selain komentar yang bisa ditebak—bahwa kisahnya menyeramkan, seperti memang seharusnya sebuah cerita aneh di malam Natal dalam rumah tua—aku tak ingat ada yang langsung berkata apa pun… sampai seseorang berkomentar bahwa ini satu-satunya kisah yang pernah ia dengar di mana penampakan seperti itu dialami oleh seorang anak.
Kejadiannya, kalau boleh kusebutkan, terjadi di rumah tua yang sangat mirip dengan tempat kami berkumpul malam itu—penampakan mengerikan yang dialami seorang bocah kecil yang tidur sekamar dengan ibunya. Bocah itu terbangun dalam ketakutan dan membangunkan sang ibu—bukan untuk ditenangkan agar bisa tidur lagi, tapi justru untuk membuat ibunya juga melihat makhluk mengerikan itu, sebelum wanita itu sempat menenangkan anaknya.
Komentar itulah yang akhirnya memancing tanggapan dari Douglas—bukan langsung malam itu, tapi beberapa saat kemudian. Komentar yang membawa pada satu hal yang menarik, dan inilah yang ingin kutekankan.
Seseorang menceritakan kisah lain, tapi tak terlalu berdampak. Kulihat Douglas tidak benar-benar mendengarkan, dan aku langsung merasa ia menyimpan sesuatu. Kami hanya tinggal menunggu. Dan memang, kami menunggu sampai dua malam berikutnya. Namun malam itu juga, sebelum bubar, ia mulai memberi isyarat.
“Aku setuju soal cerita Griffin—atau hantu atau apalah itu. Fakta bahwa hantu itu muncul pertama kali ke bocah kecil di usia semuda itu memang memberi kesan yang lain. Tapi itu bukan satu-satunya kejadian jenis ini yang melibatkan anak-anak. Kalau satu anak saja sudah membuat ceritanya jadi lebih tegang, bagaimana kalau dua anak?”
“Tentu saja,” seru seseorang, “itu artinya ketegangan dua kali lipat lebih tegang! Dan tentu saja kami ingin dengar kisahnya!”
Masih kuingat Douglas berdiri menghadap api, membelakangi kami, kedua tangan di saku sambil menatap lawan bicaranya. “Tak ada satu orang pun, sampai malam ini, yang pernah mendengar kisah ini. Ceritanya terlalu mengerikan.”
Beberapa orang langsung berseru bahwa justru itu yang membuat ceritanya jadi paling menarik. Dengan gaya tenang dan terkendali, Douglas melirik kami satu per satu dan menambahkan, “Ini di luar nalar. Tak ada satu pun yang bisa menandinginya.”
“Dalam hal menimbulkan ketakutan?” tanyaku, penasaran.
Ia terlihat berpikir keras, seakan kesulitan mencari kata yang tepat. Ia menyeka matanya, lalu membuat ekspresi canggung. “Dalam hal… kengerian yang betul-betul mengerikan.”
“Oh, kedengarannya menggoda sekali!” seru seorang perempuan.
Douglas tidak menanggapi komentar itu. Ia menatapku, tapi seolah bukan aku yang dilihatnya—melainkan bayangan dari cerita yang akan ia sampaikan. “Untuk keburukan yang tak terjelaskan, kengerian, dan rasa sakit yang aneh.”
“Kalau begitu,” kataku, “duduklah dan mulailah bercerita.”
Ia menoleh ke perapian, menendang sepotong kayu bakar, mengamatinya sebentar, lalu kembali menghadap kami. “Aku tidak bisa langsung mulai menceritakannya. Aku harus kirim orang ke kota dulu.” Semua langsung mengeluh serempak, tak sabar, tapi ia tetap tenang dan menjelaskan, “Ceritanya sudah ditulis. Ada di dalam laci yang terkunci. Sudah bertahun-tahun tidak kubuka. Aku bisa kirim surat ke asistenku, beserta kunci laci itu agar dia bisa mengirimkan naskahnya.”
Ia tampak menyampaikan ini langsung kepadaku—seolah meminta bantuanku untuk tidak membuatnya ragu. Ia sudah menembus lapisan es yang tebal, yang terbentuk selama banyak musim dingin. Ia punya alasan untuk diam begitu lama. Yang lain merasa kesal karena cerita ditunda, tapi justru keraguan dan kehati-hatiannyalah yang membuatku terkesan.
Aku mendesaknya untuk segera mengirim surat, agar kami bisa mendengar kisahnya secepat mungkin. Lalu kutanya, apakah pengalaman itu adalah miliknya sendiri.
“Oh, syukurlah, bukan!” jawabnya cepat.
“Lalu catatan itu milikmu? Kau yang mencatatnya?”
“Hanya kesan-kesannya. Kesan itu kutangkap di sini,” katanya, sambil mengetuk dadanya. “Dan belum pernah hilang.”
“Jadi manuskripnya?”
“Ditulis dengan tinta yang sudah pudar… dalam tulisan tangan yang amat indah.” Ia terdiam sejenak. “Tulisan seorang perempuan. Ia sudah meninggal dua puluh tahun lalu. Ia mengirimkannya padaku sebelum meninggal.”
Sekarang semua memperhatikan, dan seperti biasa, pasti ada saja yang menggoda, atau minimal menyimpulkan sesuatu. Tapi kalau pun Douglas mengabaikannya tanpa senyum, ia juga tidak tampak terganggu.
“Ia perempuan yang sangat menarik, meski sepuluh tahun lebih tua dariku. Ia pengasuh adikku,” katanya tenang. “Ia perempuan paling menyenangkan yang pernah kutemui dalam pekerjaan tersebut. Ia pantas ditempatkan di mana saja. Kejadiannya sudah lama sekali—dan ceritanya pun jauh sebelum itu. Waktu itu aku kuliah di Trinity, dan saat pulang di musim panas tahun kedua, aku bertemu lagi dengannya di rumah. Tahun itu aku sering di rumah. Cuacanya indah sekali. Di waktu luangnya, kami sering berjalan-jalan dan mengobrol di taman. Ia sangat cerdas dan menyenangkan. Oh ya, jangan tertawa—aku sangat menyukainya, dan sampai sekarang aku senang membayangkan bahwa ia pun menyukaiku. Kalau tidak, ia takkan pernah menceritakan semuanya padaku.”
Ia melanjutkan, “Ia tidak pernah bercerita kepada siapa pun. Bukan cuma karena ia bilang begitu, tapi aku tahu dari caranya. Aku yakin. Dan nanti kau juga akan tahu kenapa.”
“Karena kejadiannya begitu menyeramkan?” tebakku.
Ia menatapku lekat-lekat. “Kau akan tahu sendiri,” ulangnya. “Kau akan mengetahuinya.”
Aku menatap balik. “Aku mengerti. Ia sedang jatuh cinta.”
Douglas tertawa, untuk pertama kalinya. “Pengamatanmu memang tajam. Ya, ia jatuh cinta. Atau setidaknya, pernah jatuh cinta. Itu tak bisa ia sembunyikan dalam ceritanya. Aku melihatnya, dan ia tahu aku melihat itu—tapi kami tidak membicarakan hal tersebut.”
“Aku masih ingat waktu dan tempatnya,” lanjutnya. “Sudut halaman rumput, di bawah rindangnya pohon beech yang besar, dan siang musim panas yang begitu panjang dan panas. Bukan tempat yang cocok untuk cerita menyeramkan, tapi—oh…”
Ia meninggalkan perapian dan duduk kembali di kursinya.
“Kau akan menerima paketnya hari Kamis pagi?” tanyaku.
“Mungkin tidak sampai pengiriman pos kedua.”
“Kalau begitu, setelah makan malam saja—”
“Kalian semua akan berkumpul di sini?” Ia memandang kami satu per satu. “Tak ada yang pergi?” Nadanya terdengar seperti harapan.
“Semua akan tetap di sini!”
“Aku juga!” dan “Aku juga!” seru para perempuan yang tadinya sudah punya rencana pergi. Namun Mrs. Griffin tampaknya masih butuh sedikit kepastian. “Sebenarnya… siapa sih orang yang dia cintai itu?”
“Cerita akan menjawabnya,” jawabku mewakili Douglas.
“Oh, aku tak sabar menunggu ceritanya!”
“Cerita itu tidak akan menjelaskan apa-apa,” sahut Douglas. “Setidaknya bukan secara langsung dan vulgar.”
“Sayang sekali. Karena cuma itu satu-satunya cara yang bisa kupahami.”
“Kalau begitu kau saja yang bercerita, Douglas?” celetuk seseorang.
Douglas langsung berdiri. “Ya—besok. Sekarang aku harus tidur. Selamat malam.” Ia segera mengambil tempat lilin dan pergi begitu saja, meninggalkan kami dalam sedikit kebingungan. Dari ujung aula besar berwarna cokelat gelap itu, kami masih bisa mendengar langkahnya menaiki tangga.
Mrs. Griffin lalu berkata, “Yah, kalaupun aku tidak tahu siapa yang dicintainya… aku tahu siapa yang mencintai dia.”
“Perempuan itu sepuluh tahun lebih tua,” kata suaminya.
“Raison de plus—apalagi di usia segitu! Tapi aku suka, sih… bagaimana ia menyimpan cerita ini begitu lama.”
“Empat puluh tahun!” tambah Griffin.
“Dan akhirnya meledak juga.”
“Ledakan itu,” kataku, “akan menjadikan Kamis malam sangat luar biasa.” Dan semua orang setuju. Karena itu, kami pun kehilangan minat pada segala hal lain malam itu. Cerita terakhir—meskipun terasa belum lengkap dan lebih seperti pembukaan serial—sudah disampaikan. Kami bersalaman dan, seperti yang dikatakan seseorang, “menancapkan lilin masing-masing”, lalu pergi tidur.
Besoknya aku tahu, surat berisi kunci sudah dikirim lewat pos pertama ke apartemennya di London. Namun, mungkin justru karena semua orang sudah tahu itu, kami membiarkannya tidak diganggu sampai selesai makan malam. Hingga malam tiba dan suasana terasa paling cocok untuk menyambut kisah yang kami tunggu.
Saat itulah ia mulai bercerita seperti yang kami harapkan—dan bahkan lebih. Duduk kembali di depan api, seperti malam sebelumnya, ia memulai dengan prolog singkat untuk membantu kami memahami narasi yang akan dibacakan. Izinkan aku jelaskan dengan tegas di sini: cerita yang akan kusampaikan ini berasal dari salinan persis yang kubuat belakangan, dari naskah aslinya.
Sebelum meninggal—saat ajalnya sudah terasa dekat—Douglas mempercayakan naskah itu kepadaku. Ia menerimanya di hari ketiga, dan malam keempat, di tempat yang sama ini, ia mulai membacanya untuk kami yang sudah diam menanti, dengan pengaruh yang sungguh luar biasa.
Para perempuan yang tadinya bersumpah akan tetap tinggal, tentu saja—syukurlah—tidak jadi. Mereka tetap pergi sesuai rencana, tapi pergi dengan rasa ingin tahu yang menggebu karena cuplikan-cuplikan yang sudah sempat Douglas beri. Hal itu justru membuat kelompok kecil yang tersisa semakin erat dan fokus, menyatu di depan perapian dengan getaran rasa yang sama.
Hal pertama yang ia ungkapkan adalah bahwa pernyataan tertulis itu sebenarnya dimulai dari tengah—kisahnya sendiri sudah “berjalan” ketika catatan itu mulai ditulis. Maka, informasi penting yang perlu kami pahami adalah ini: teman lamanya, si penulis naskah, adalah anak bungsu dari beberapa putri seorang pendeta miskin di pedesaan. Saat berusia 20 tahun, ia pertama kali mencari pekerjaan sebagai pengasuh. Ia datang ke London dengan perasaan campur aduk, untuk menjawab langsung sebuah iklan yang sebelumnya telah membawanya ke dalam korespondensi singkat dengan si pengiklan.
Dan orang yang menyambutnya di rumah besar di Harley Street—yang baginya tampak megah dan mengintimidasi—ternyata adalah seorang pria lajang mapan, tipe lelaki yang rasanya cuma bisa dijumpai dalam mimpi atau novel klasik tua, apalagi bagi gadis gugup dari desa di Hampshire.
Ia pria yang mudah ditebak tipenya—dan untungnya, tipe seperti ini tak pernah punah: tampan, percaya diri, menyenangkan, ramah, ceria, dan penuh perhatian. Ia terlihat gagah dan mengesankan, tapi yang paling membekas dan membuat sang gadis punya keberanian untuk menerima tawaran itu adalah caranya berbicara—seolah ia sedang meminta bantuan darinya, bukan sekadar mempekerjakannya. Seolah-olah tawaran itu adalah kehormatan bagi sang pria, bukan bagi dirinya.
Ia terlihat kaya raya, tetapi boros luar biasa. Ia tampak seperti orang yang terbakar oleh kemewahan, penampilan, gaya hidup mahal, dan pesonanya dalam memperlakukan perempuan. Rumahnya di kota besar dipenuhi benda-benda eksotis dari berbagai penjuru dunia dan trofi hasil perburuannya. Namun tugas sang pengasuh akan dimulai bukan di sana—melainkan di rumah pedesaan milik keluarganya di Essex, dan ia diminta segera berangkat ke sana.
Setelah kedua orangtuanya meninggal di India, seorang pria lajang—yang tak pernah menganggap dirinya punya kesabaran atau pengalaman mengurus anak—mendadak jadi wali dari keponakan laki-laki dan perempuannya. Dua anak dari adik lelakinya yang seorang tentara, yang juga telah tiada dua tahun sebelumnya. Dan kini, dua “cicak kecil” itu—begitu ia menyebutnya dengan simpati—malah jadi tanggung jawab besar dalam hidupnya yang sudah repot sendiri. Ia mengaku sempat keliru dalam beberapa hal, tapi tak bisa dipungkiri: ia benar-benar iba pada mereka dan sudah berusaha semampunya.
Sebagai langkah awal, ia mengirim keduanya ke rumah pedesaannya—sebuah tempat bernama Bly yang sehat dan aman. Di sana mereka diasuh oleh orang-orang terbaik yang bisa ia temukan, bahkan sampai merelakan beberapa pelayannya sendiri ikut tinggal demi memastikan segalanya berjalan baik. Ia juga turun langsung mengunjungi mereka bila ada waktu luang. Masalahnya, keluarga mereka nyaris tak ada lagi, dan urusan pribadinya menyita hampir seluruh waktu.
Untuk mengelola rumah tangga di Bly, ia menugaskan Mrs. Grose, wanita yang dulu bekerja sebagai pelayan ibunya. Sekarang, Mrs. Grose menjabat sebagai pengurus rumah tangga, sekaligus—karena memang sedang tidak ada pengganti—mengasuh si adik perempuan, Flora, yang untungnya sangat ia sayangi meski bukan anak kandungnya. Ada juga koki, pembantu rumah, penjaga sapi perah, seekor poni tua, seorang pengurus kuda tua, dan tukang kebun tua. Semuanya orang baik-baik.
Namun, posisi utama tetap untuk seorang governess muda, yang nantinya akan memegang otoritas tertinggi di atas semua orang itu. Ia juga harus siap menjaga si kakak laki-laki, Miles, yang meski masih kecil, sudah dikirim ke sekolah asrama. Saat cerita ini dimulai, libur sekolah hampir tiba dan anak itu akan segera kembali.
Sebelumnya, mereka sempat diasuh oleh seorang governess yang sangat baik—”terhormat” menurut Douglas. Sayangnya, wanita itu meninggal dunia secara mendadak. Peristiwa itulah yang kemudian membuat Miles dikirim ke sekolah, karena tak ada pilihan lain. Sejak saat itu, Mrs. Grose melakukan yang ia bisa untuk mendampingi Flora dalam soal tata krama dan kebiasaan sehari-hari.
Sampai di titik ini, Douglas menyampaikan ceritanya dengan serius—sampai seorang dari kami menyela, “Lalu, si governess sebelumnya itu meninggal karena apa? Karena terlalu terhormat?”
Douglas menjawab cepat, “Itu akan terungkap nanti. Aku tidak mau mendahului ceritanya.”
“Maaf,” kata si penanya, “tapi bukankah kau justru sedang mendahului ceritanya?”
“Kalau aku yang jadi penerusnya,” kataku iseng, “aku pasti ingin tahu dulu: pekerjaan ini membawa risiko bagi jiwaku atau tidak?”
Douglas melanjutkan kalimatku, “Memang, dia ingin tahu. Dan dia akhirnya tahu. Besok malam kalian akan dengar sendiri apa yang dia pelajari. Tapi awalnya, semua ini terasa agak menakutkan baginya. Dia masih muda, belum berpengalaman, dan agak penakut. Yang dia lihat adalah tanggung jawab besar dengan sedikit sekali teman. Kesepian yang benar-benar nyata. Maka dia pun ragu—butuh dua hari untuk berpikir dan menimbang-nimbang. Tapi gaji yang ditawarkan jauh lebih tinggi dari yang biasa ia dapat, dan pada pertemuan kedua, dia akhirnya menyanggupi. Ia menerima pekerjaan itu.”
Douglas berhenti sejenak, lalu aku menyambung setengah bercanda, “Jadi moral ceritanya: dia tergoda pesona pria muda nan tampan itu. Ia takluk.”
Douglas bangkit berdiri, seperti malam sebelumnya, berjalan ke perapian, menyentuh sebatang kayu bakar dengan kakinya, lalu berdiri sejenak membelakangi kami.
“Dia hanya dua kali bertemu dengannya.”
“Justru di situlah indahnya rasa itu,” kataku spontan.
Mengejutkanku sedikit, Douglas berbalik dan menatapku. “Ya, memang itu yang membuatnya indah. Ada orang lain, lho, yang tidak jatuh hati kepadanya.” Ia melanjutkan, “Dia mengatakan secara jujur semua kesulitannya—bahwa banyak pelamar sebelumnya mundur karena syarat-syarat yang menurut mereka aneh. Semuanya terdengar membosankan, bahkan agak mencurigakan. Terutama karena ada satu syarat utama.”
“Syarat apa?”
“Bahwa dia tidak boleh mengganggunya—sama sekali tidak. Tidak boleh meminta bantuan, tidak boleh mengeluh, tidak boleh menulis surat apa pun. Semua hal harus ditangani sendiri. Dana akan dikirim lewat kuasa hukumnya. Dan selebihnya, dia harus dibiarkan hidup tenang. Gadis itu menyanggupi, dan katanya saat pria itu menggenggam tangannya sejenak, berterima kasih atas pengorbanannya, dia sudah merasa diberi balasan yang cukup.”
“Dan itu saja imbalannya?” tanya salah satu dari para wanita.
“Dia tak pernah bertemu lagi dengannya.”
“Oh!” gumam si wanita itu.
Douglas pun kembali meninggalkan kami. Dan itulah satu-satunya komentar penting malam itu—sampai malam berikutnya, ketika ia duduk di kursi terbaik dekat perapian, membuka sebuah album kuno bertepi emas dengan sampul merah yang mulai pudar.
Kisah itu ternyata memakan beberapa malam. Namun pada malam pertama, wanita yang tadi sempat bertanya, kembali angkat suara, “Judul kisah ini apa?”
“Aku tak memberinya judul.”
“Oh, kalau aku sih, sudah punya judul!” kataku cepat.
Namun Douglas tak menanggapi. Ia sudah mulai membaca, dengan suara bening dan tenang, seolah membacakan langsung dari naskah yang ditulis tangan oleh seseorang yang—begitu kata Douglas—punya gaya yang memesona.
Dukung Penulis/Penerjemah Novel Favoritmu
Login untuk memberikan vote dukungan
💖 Suka baca cerita ini?
Bantu KlikNovel menerjemahkan lebih banyak novel public domain seperti The Turn of the Screw karya Henry James ini. Scan QR Code untuk berdonasi via Saweria 🙏
📝 Belum ada komentar untuk bab ini. Jadilah yang pertama berkomentar!
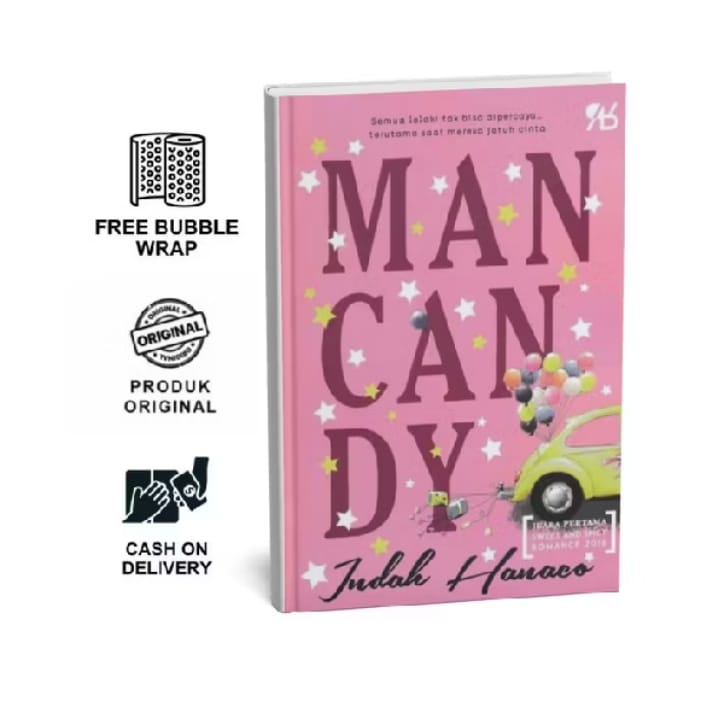

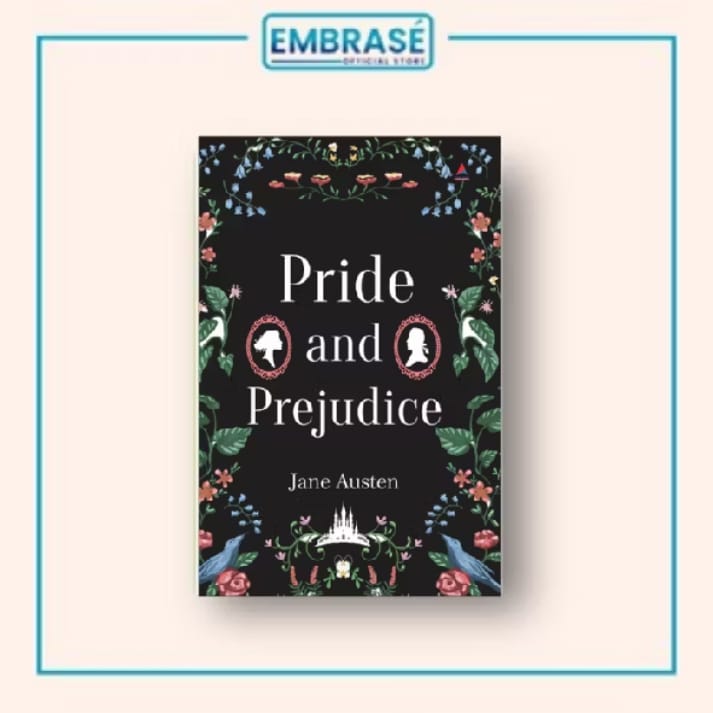
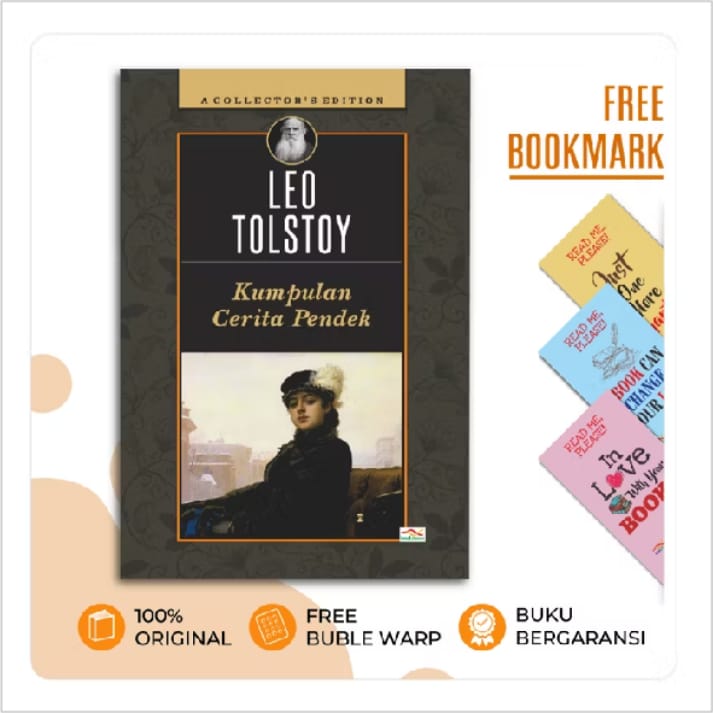

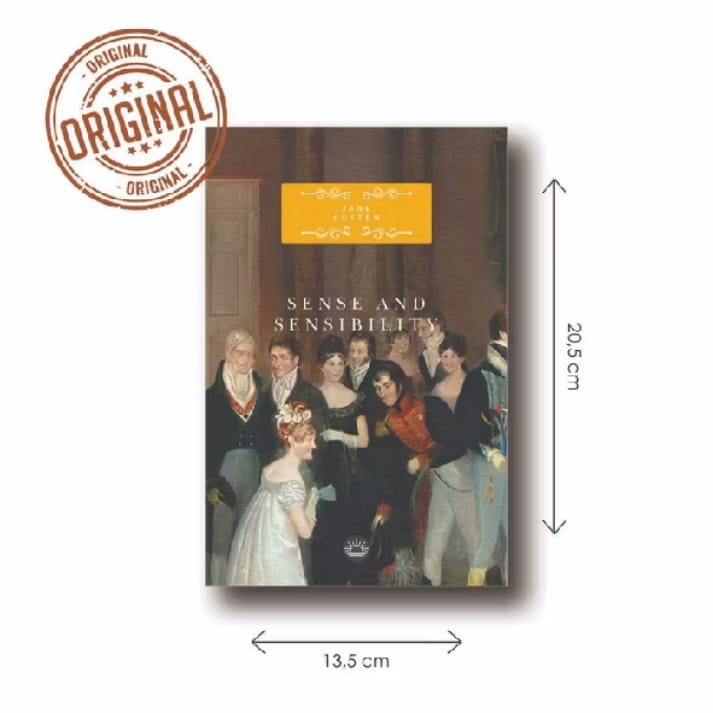
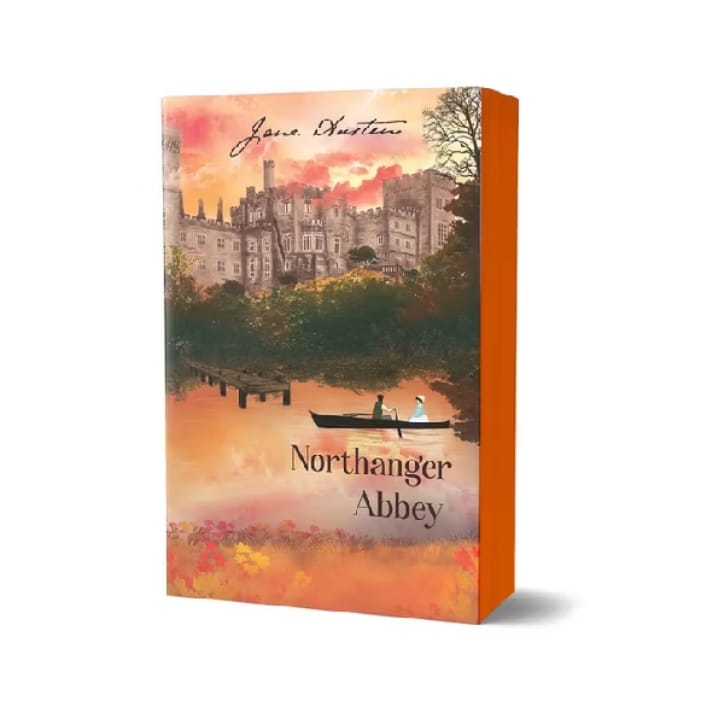

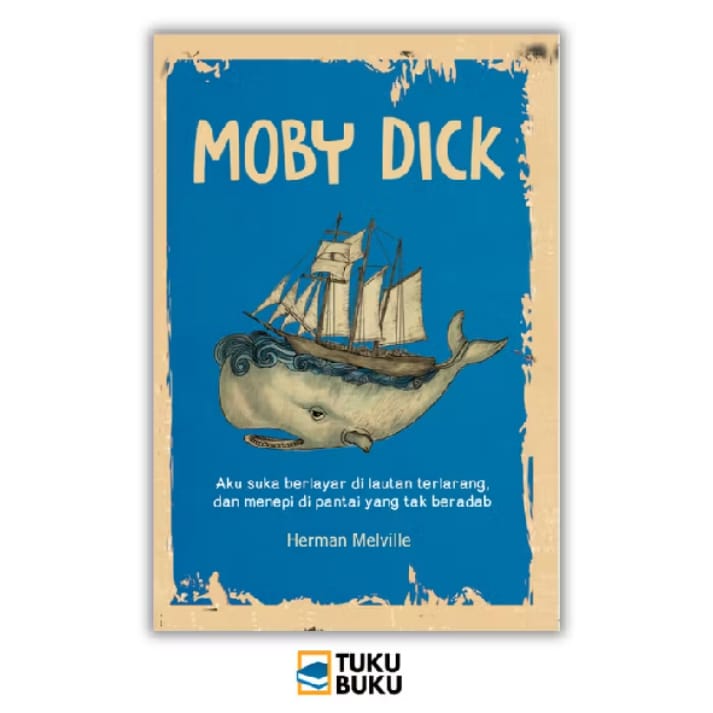
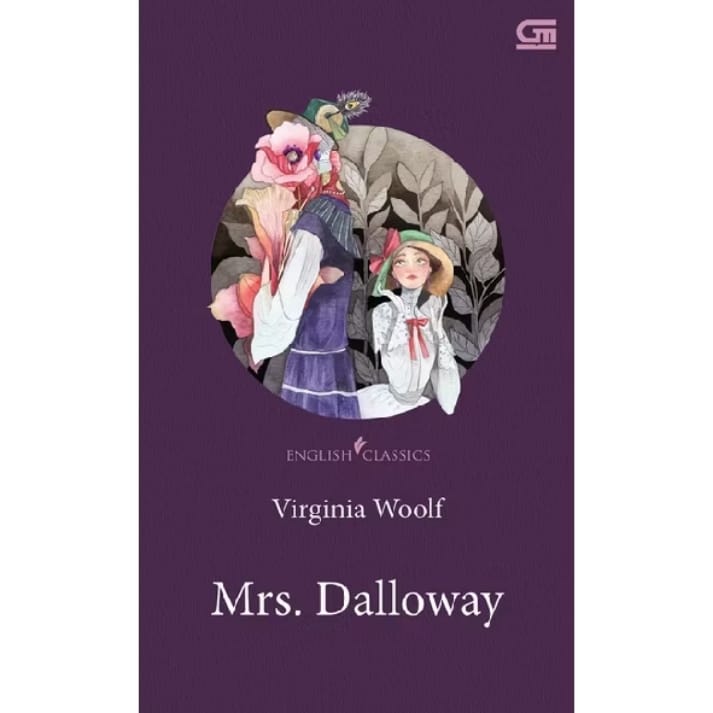


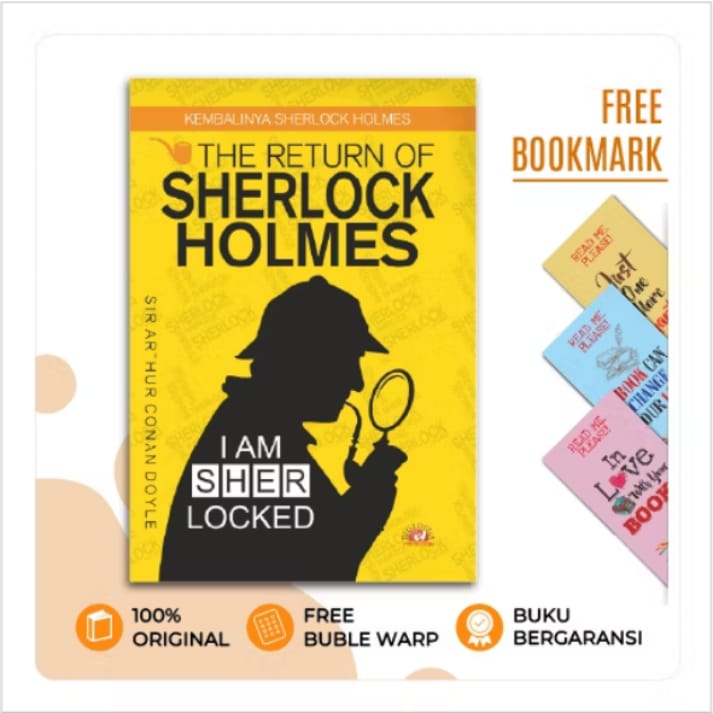
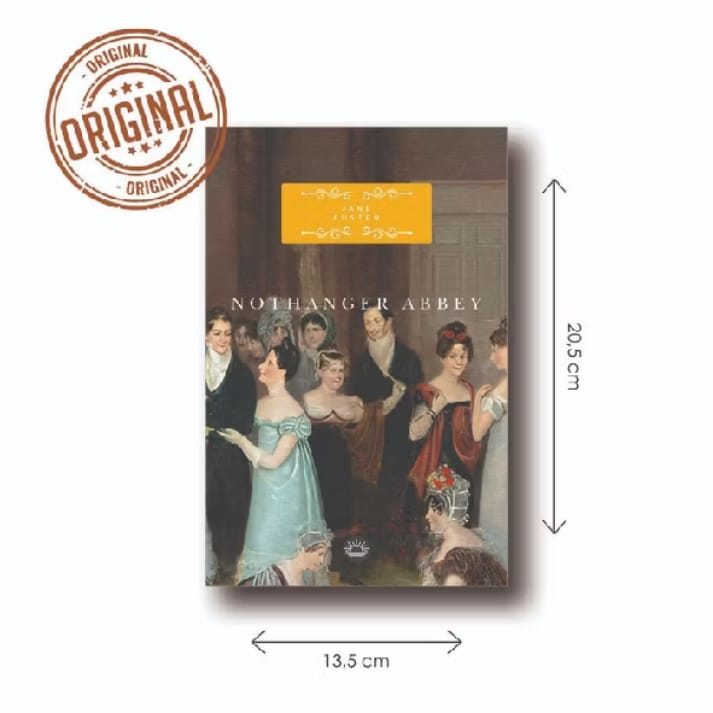

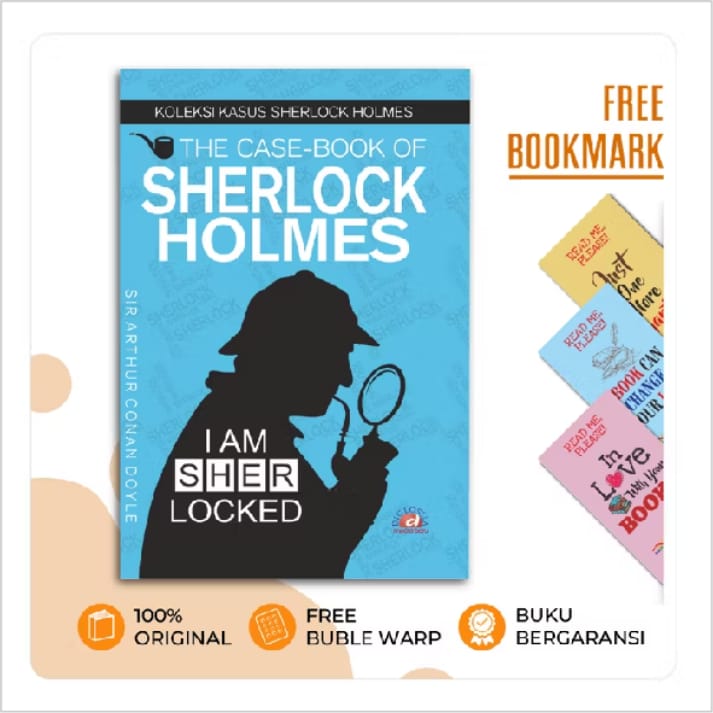
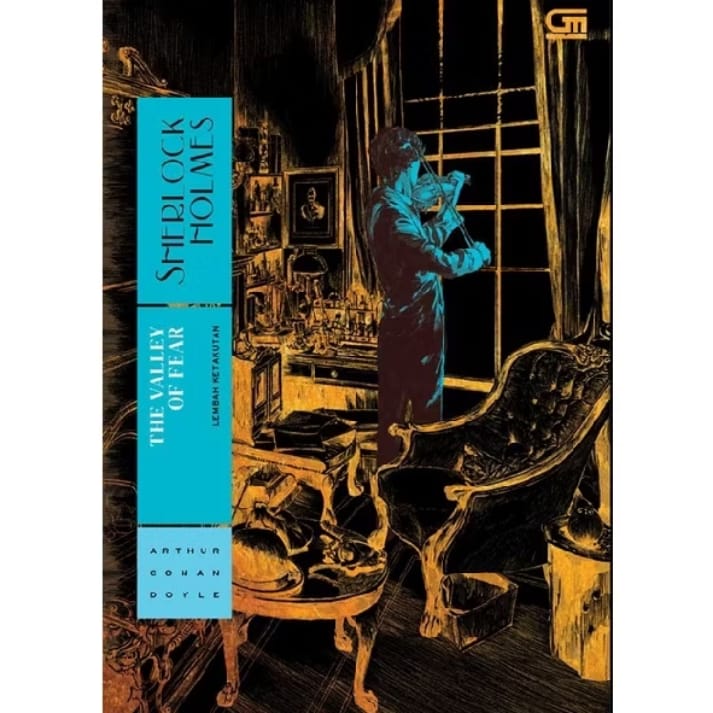

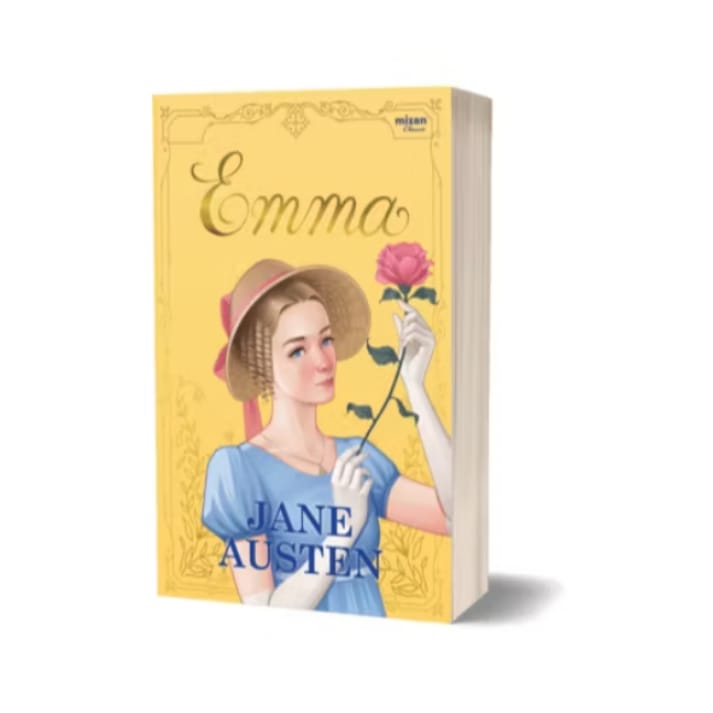


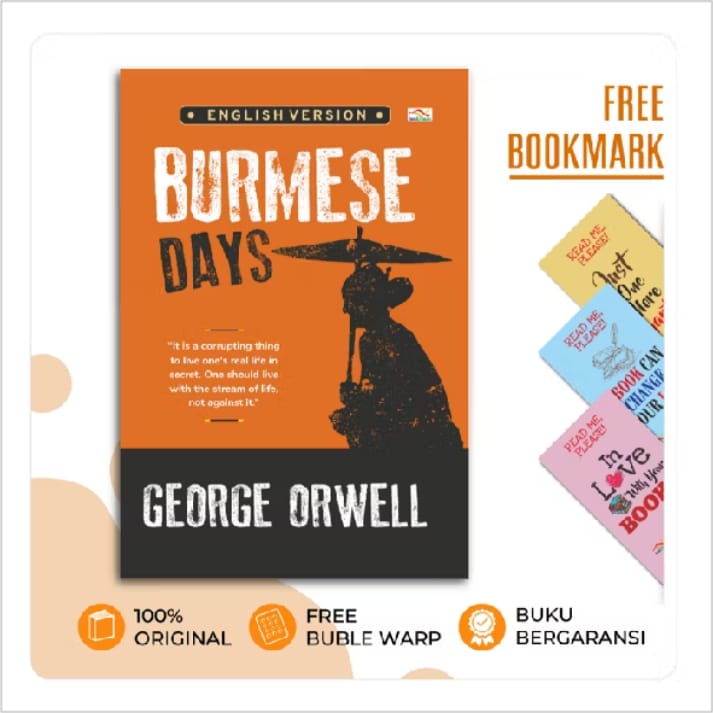
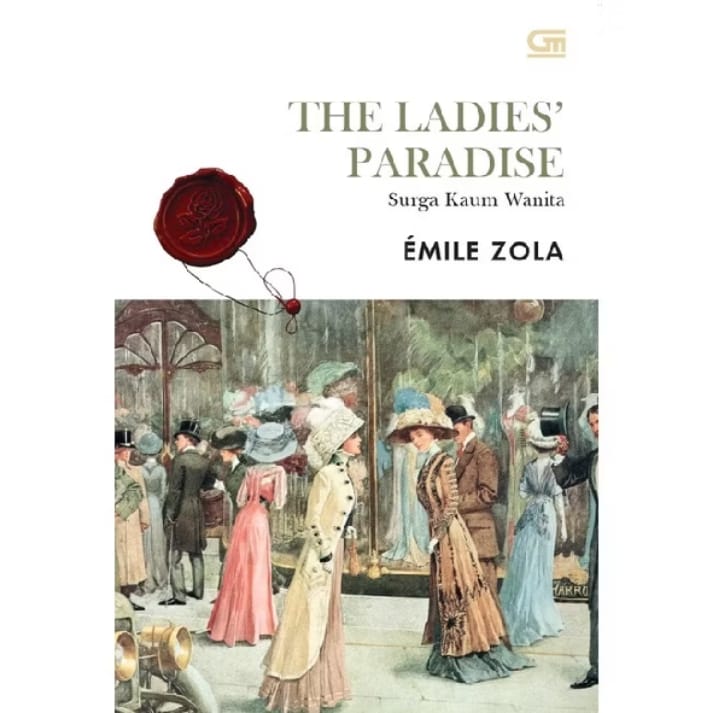
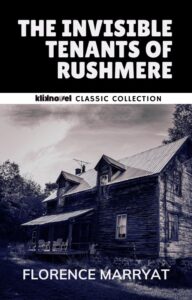
Silakan login untuk meninggalkan komentar.